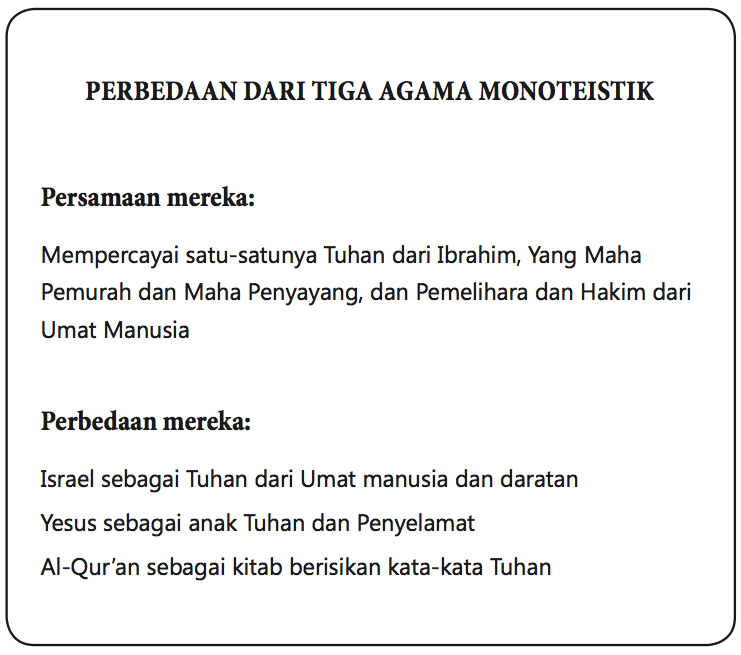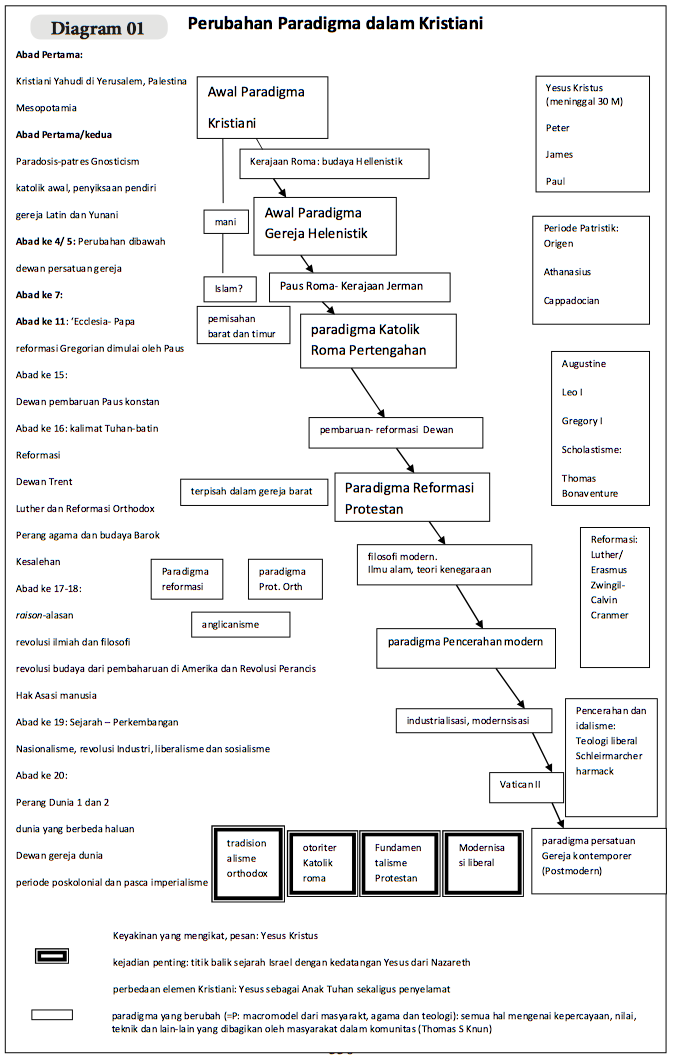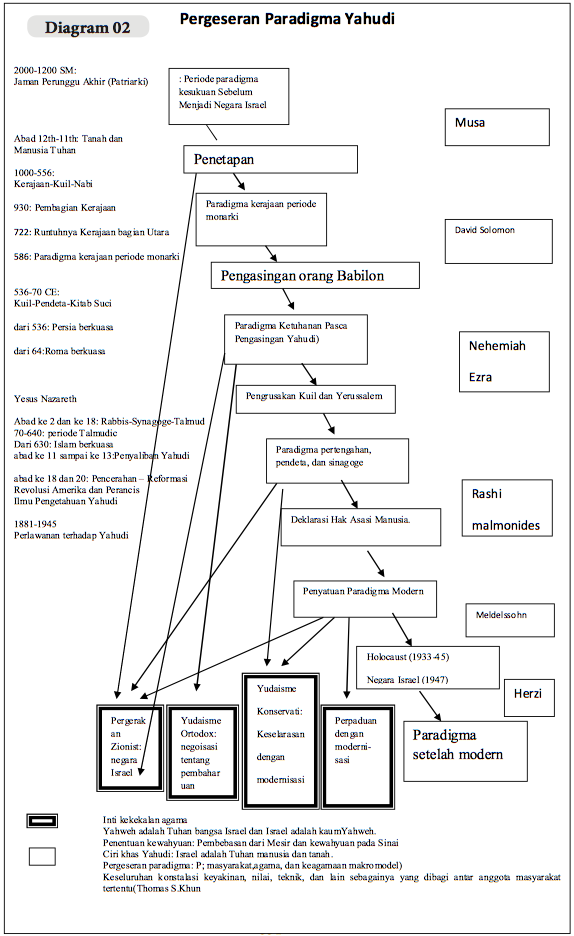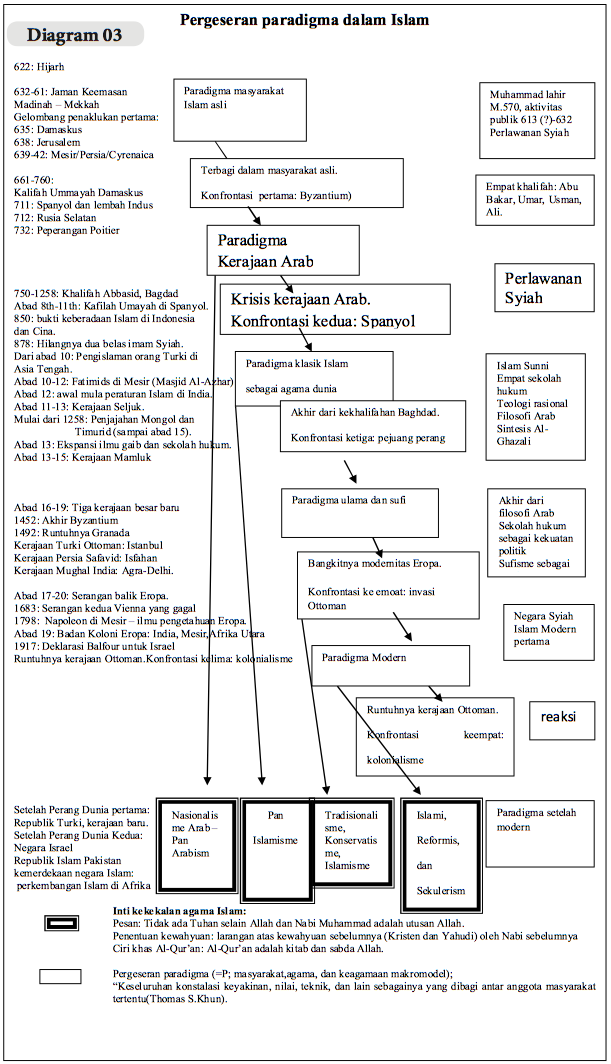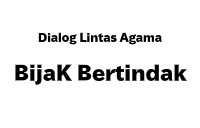![]()
BEBERAPA DOKUMEN PENTING DARI DIALOG
LINTAS AGAMA DI TUBINGEN
“Agama Dunia sebagai Faktor di Dunia Politik”
7-8 Mei 2007, Tubingen, Jerman
TIGA AGAMA IBRAHAM
PERGOLAKAN HISTORIS DAN
TANTANGAN MASA KINI
Pidato oleh:
Profesor Hans Kung
Profesor Emeritus, Universitas Tubingen
Pengantar
Saat ini kita menghadapi ancaman prasangka—kali ini bukan datang dari kaum Yahudi, tapi kaum Muslim. Tampaknya mereka semua terhasut oleh agama mereka dan hasutan itu berpotensi menimbulkan kekacauan. Sebaliknya kaum Kristen menyebarkan perdamaian karena agama mereka mengajarkan kebaikan, perdamaian dan cinta kasih. Itu adalah hal yang sangat indah!
Tentu saja ada banyak masalah, khususnya di Eropa yang jumlah kaum Muslimnya sedikit. Tapi marilah kita bersikap adil: kita adalah penduduk negara demokrasi yang menentang pernikahan paksa, tekanan terhadap wanita, pembunuhan atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya yang mengatasnamakan martabat. Tapi banyak pula kaum Muslim yang menentang hal itu. Mereka sedih dengan fakta bahwa pelaknatan terhadap Muslim sama sekali tidak membedakan antara Muslim dan Islam. Mereka tidak mengenal diri mereka dalam pigura Islam karena mereka ingin menjadi penganut Islam yang loyal.
Marilah kita bersikap adil: mereka yang membuat ‘Islam’ ber- tanggung jawab atas penculikan, bom bunuh diri, atau bom mobil adalah orang-orang ekstremis yang dangkal pikirannya. Pada saat yang sama mereka juga mengutuk ‘kaum Kristen’ dan ‘Kaum Yahudi” atas tindakan barbar mereka terhadap tawanan, serangan udara dan serangan tank (sekitar 10,000 penduduk sipil telah terbunuh di Irak). Itu dilakukan oleh tentara Amerika. Dan juga serangan teroris Israel terhadap Palestina. Setelah tiga tahun perang, sebagian besar penduduk Amerika menyadari bahwa pihak-pihak yang menyebut perang di Timur Tengah dan sekitarnya itu berkedok “perang untuk kepentingan demokrasi” dan “perang melawan teror”. Faktanya perang itu adalah memperebutkan minyak. Mereka gagal menutupi kedok itu.
Di Perkuliahan Global Ethic di Tubingen tahun 2003, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menegaskan: Tidak ada satu pun agama itu harus dilaknat karena perubahan moral beberapa penganutnya. Sebagai orang Kristen, saya tidak akan berharap agama saya dihakimi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Crusaders (pasukan Perang Salib) atau Inquisition. Saya juga harus berhati-hati untuk menghakimi agama orang lain atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teroris yang mengatasnamakan agama tersebut.
Jadi sekarang saya bertanya pada Anda: Apakah kita harus tetap meneruskan aksi balas dendam yang hanya akan memperburuk keadaan?
Jawabannya adalah tidak. Karena itu hanya akan mengundang datangnya aksi kekerasan dan peperangan. Pada dasarnya semua orang di mana pun tidak menginginkan hal itu terjadi, kecuali di beberapa negara Arab dan terkadang di Amerika Serikat. Mereka disesatkan dan dibutakan oleh obsesi kekuasaan. Ideologi dan kata-kata manis di media yang diungkapkan oleh pemimpin-pemimpin yang pandai berbicara telah menumpulkan otak mereka.
“Pasukan perang salib” abad pertengahan dan modern telah melakukan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan Kristen. Tindakan mereka itu menyelewengkan lambang salib yang merupakan lambang rekonsiliasi sehingga lambang salib itu diartikan sebagai lambang peperangan melawan kaum Muslim dan Yahudi (Spanyol). Agama Kristen dan Islam telah menyebarkan pengaruh- pengaruh secara agresif dan membela agama mereka dengan kekerasan. Di lingkungan mereka, mereka telah menyebarkan ideologi peperangan, bukan perdamaian. Jadi masalahnya memang sangat rumit.
Berbagai macam informasi yang membanjiri kita setiap hari membahayakan diri kita karena informasi-informasi tersebut membuat kita kehilangan nilai diri: sikap, tingkah laku hingga cara berpakaian kita. Kita mungkin pernah mendengar pendapat yang diutarakan oleh agamawan bahwa terasa sulit untuk memahami situasi dengan jelas karena keterlibatan yang terlalu dalam. Jadi beberapa kaum terpelajar, misalnya dalam bidang sosiologi, berkonsentrasi pada ilmu mikro dan tidak lagi berpikir dalam konteks yang lebih luas; atau mereka tidak lagi punya kemampuan untuk berpikir dalam konteks yang lebih luas. Di sini, saya yakin, dibutuhkan kategori-kategori baru untuk membuat perubahan.
Jadi untuk waktu satu jam atau lebih saat ini, saya menawarkan orientasi dasar tentang tiga agama Abraham, Yahudi, Kristen dan Islam. Intinya: Saya ingin menanyakan tiga pertanyaan yang rumit: I. Pusat dan Dasar Kekekalan, apa yang mutlak dilindungi: II. Perubahan Cara Berpikir: apa yang dapat melindungi, III: Tantangan-tantangan masa kini: tugas-tugas yang harus kita lakukan.
Pusat dan Dasar Kekekalan
Ini adalah pertanyaan yang sangat praktis: Dalam masing-masing agama kita apa yang mutlak dilindungi? Di agama Kristen,Yahudi, dan Islamada dua pernyataan yang ekstrem: beberapa mengatakan “Tidak ada satu pun yang harus dilindungi kecuali agama kita”, sedangkan yang lain berpendapat “Semuanya harus dilindungi.”
Penganut Kristen Sekuler mengatakan bahwa “tidak satu pun” harus dilindungi: sering kali mereka tidak percaya dengan Allah atau Anak Allah, mereka mengabaikan gereja dan mengacuhkan khotbah dan sakramen.
Tetapi mereka peduli dengan peninggalan sejarah: gereja-gereja katedral atau Johann Sebastian Bach, estetika peribadatan Ortodoks dan Paus. Menurut mereka Paus adalah pilar dari peraturan yang telah dibuat meskipun mereka menolak moralitas seksual Paus dan sifat otoriter dan terkadang mereka juga agnostis dan ateis.
Penganut Yahudi sekuler juga mengatakan “tidak satu pun harus dilindungi”: mereka tidak percaya dengan Tuhan Abraham dan patriarki, mereka tidak yakin percaya dengan janji-janjinya, mereka mengabaikan doa-doa dan ritual sinagoge dan aliran ultra Ortodok yang konyol.
Mereka telah menemukan agama pengganti yang modern untuk penganut agama Yahudi mereka: Israel dan Holocaust. Agama peng- ganti ini selain menciptakan identitas tersendiri bagi kaum Yahudi juga menciptakan solidaritas antara penganut Yahudi sekuler. Tapi sering kali, pada saat yang bersamaan, hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan bernada terorisme melawan bangsa Arab yang merendahkan hak asasi manusia.
Penganut Muslim sekuler juga mengatakan bahwa “tidak satu pun harus dilindungi”. Mereka tidak yakin dengan adanya satu Tuhan, mereka tidak membaca Al-Qur’an, Nabi Muhammad Saw. bukanlah seorang Nabi. Mereka juga menolak syariah-syariah Islam. Mereka juga mengabaikan lima pilar dalam agama Islam.
Perwujudan Islam yang terbaik adalah isi keagamaannya digunakan sebagai instrumen politik Islam, Arab, dan nasionalisme.
Sekarang Anda dapat memahami bahwa reaksi balik dari “Tidak melindungi apa-apa” adalah “Melindungi semuanya”. Semuanya ber- arti keadaan dulu dan sekarang tetap sama.
“Tidak satu pun dogma Katolik yang dapat dirusak karena itu akan merusak semua tatanan yang sudah lama ada” kata integralis dan tradisionalis Roma.
“Halakhah tidak akan diabaikan; sabda Tuhan (Adonai) melandasi setiap perkataan,” protes penganut Yahudi ultra-Orthodox.
“Ayat-ayat Al-Qur’an tidak ada yang diabaikan, masing-masing ayat adalah sabda Allah,” tegas penganut Islam.
Anda melihat: Konflik-konflik yang terjadi, sebelumnya sudah direncanakan dengan matang, tidak hanya antara tiga agama tetapi di dalam ketiga agama tersebut. Konflik-konflik itu seringkali dilakukan secara militan dan agresif, masing-masing mengganggu agama satu sama lain.
Tapi yakinlah bahwa kenyataan yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Di banyak negara, jika tidak terdapat faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial, maka posisi-posisi yang ekstrem tidak akan terbentuk. Terdapat penganut-penganut Yahudi, Kristen dan Islam yang meskipun berbeda dari penganut-penganut kebanyakan karena mereka malas beribadah dan mengabaikan aturan-aturan agama mereka tetapi mereka juga tidak bersedia melepaskan diri mereka dari ikatan agama yang mereka anut. Contohnya adalah banyak penganut Katolik tidak menerapkan dogma dan pelajaran moral yang diajarkan oleh gereja Roma dan banyak penganut Protestan yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran dalam Kitab Injil, atau penganut Yahudi yang tidak memedulikan Halakhah atau penganut Muslim yang tidak mengamalkan syariat-syariat agama Islam secara sungguh-sungguh.
Pendapat saya adalah: jika kita tidak mengaca pada sejarah dan manifestasinya, tetapi hanya mengacu pada dokumen-dokumen dasar, testimoni-testimoni original, maksud saya adalah “kitab suci” dari masing-masing agama—jika kita melihat pada Kitab Suci orang Yahudi, Kitab Perjanjian Baru dan Al-Qur’an—tidak diragukan lagi bahwa “penerimaan” (hal-hal yang wajib diterima) dalam agama tersebut tidak melulu identik dengan hal-hal “yang sudah ada” (yang sudah ada pada saat itu), dan itulah yang menjadi “inti”, “pusat” dari satu agama telah dijabarkan dalam “kitab suci” agama tersebut. Jadi pertanyaan yang muncul sangatlah praktikal: hal-hal valid apakah yang benar- benar dapat diterima dan terus merekatkan elemen-elemen penting di masing-masing agama kita? Haruslah jelas bahwasanya tidak semua hal harus di jaga keasliannya. Tapi yang harus dilindungi adalah “inti dari keyakinan” itu, pusat keyakinan itu dan dasar-dasar agama, kitab- kitab suci, keyakinan! Seperti yang dikatakan oleh John XXIII dalam pembukaan pidatonya yang terkenal di Vatican Council yang kedua, di mana saya berperan serta sebagai Penasihat agama bersama dengan teman baik saya Joseph Ratzinger yang sekarang menjadi Paus Benedict XVI. Tapi Anda menanyakan beberapa pertanyaan yang spesifik dan saya memberikan jawaban yang mendasar dan singkat:
Anda bisa menanyakan
1. Apa yang harus dijaga keaslian agama Kristen agar tidak kehilangan “jiwa”?
- Jawabannya: kita tidak usah memedulikan kritik dan interpretasi historis, literal atau sosiologis: (setelah mempertimbangkan dasar- dasar dokumen agama Kristen yang telah berubah menjadi doku- men normatif dan mempunyai nilai sejarah yang penting,) setelah mempertimbangkan Kitab Perjanjian Baru (dapat dilihat di Kitab Injilnya kaum Yahudi), isi utama keyakinannya adalah Yesus Kristus: Sebagai Tuhan Raja dan Anak dari Tuhan Abraham. Tidak akan ada keyakinan terhadap agama Kristen, tidak akan ada agama Kristen tanpa adanya pengakuan “Yesus adalah Tuhan Raja, Allah dan Anak Allah!” (1. Kor: Iltous kyrios). Nama Yesus Kristus menunjukkan dinamika “pusat Perjanjian Baru” (yang tidak harus dipahami dengan cara yang statis).
Anda bisa menanyakan
2. Apa yang harus dijaga keaslian agama Yahudi agar tidak kehilangan “jiwa”?
- Jawaban saya adalah: kita tidak usah memedulikan kritik dan interpretasi historis, literal atau sosiologis: (setelah mempertim- bangkan dasar-dasar dokumen agama yang telah berubah menjadi dokumen normatif dan mempunyai nilai sejarah yang penting,) setelah mempertimbangkan Kitab Injil kaum Yahudi, isi utama keyakinannya adalah satu Tuhan dan bangsa Israel. Tidak akan ada keyakinan terhadap bangsa Israel,tidak akan ada Kitab Injil kaum Yahudi, tidak akan ada agama Yahudi tanpa adanya pengakuan: “Yahweh (Adonai) adalah Tuhan bangsa Israel, dan Israel adalah umat Yahweh!”
Anda bisa menanyakan
3. Apa yang harus dijaga keaslian agama Islam agar tidak kehilangan nilai “ketundukkan pada Tuhan”?
- Jawaban saya adalah: tidak peduli betapa menjemukan proses mengumpulkan, memerintah, dan menyeleksi surat-surat Al- Qur’an, untuk umat Muslim yang taat jelaslah bahwa Al-Qur’an adalah Kitab Allah. Dan meskipun ada beberapa ayat yang sebagian diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, pesan utama Al-Qur’an sangatlah jelas: Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.”
Masing-masing agama mempunyai pesan utama sendiri-sendiri. Inti dari agama Yahudi adalah hubungan bangsa Israel dengan Tuhan mereka. Bagi umat Kristen, hubungan antara Yesus Kristus dengan Tuhan dan Roh Kudus adalah awal muasal agama Kristen. Sedangkan bagi agama Islam, pesan utamanya adalah kaitan Al-Qur’an dengan Allah. Pesan itu akan terus tertanam dalam diri umat Muslim sampai kapan pun juga.
Ciri-ciri khusus dari ketiga agama tersebut adalah mereka mempunyai persamaan akan hal-hal yang harus dilindungi di mana persamaan tersebut berarti juga perbedaan mereka.
Apakah persamaan Yahudi, Kristen, dan Islam?
Keyakinan terhadap satu-satunya Tuhan Abraham, Pencipta yang
agung dan pemurah, Pelindung dan Hakim umat manusia. Mereka butuh figur agama, kitab normatif dan standar etika.
Apakah perbedaan Yahudi, Kristen dan Islam?
Yahudi: Israel adalah Tuhannya manusia dan tanah (penting untuk Israel)
Kristen: Yesus Kristus adalah adalah Tuhan dan Roh Kudus.
Islam: Al-Qur’an adalah pesan Allah sekaligus kitab Allah.
Kesimpulan dari persamaan dan perbedaan ketiga agama itu
adalah:
Originalitas dari jaman dulu
Kontinuitas mulai dari jaman dulu sampai sekarang
Identitas terlepas dari perbedaan bahasa, masyarakat, budaya, dan bangsa.
Inti dan dasar keyakinan itu tercetak dalam sejarah dan diaplikasi-kan sesuai dengan tuntutan jaman. Toynbee: tantangan dan respons! Bagi ahli agama, ahli sejarah dan yang lainnya, penting untuk meng- gabungkan sistematika agama dengan kronologi sejarah karena tanpa adanya penggabungan, sistematika agama tidak akan mempunyai dasar yang meyakinkan.
Pengaruh Perubahan Besar yang Membingungkan dan Menggelisahkan
Sering kali konstelasi baru pengaruh perubahan besar yang membingungkan dan menggelisahkan tentang masyarakat, komunitas keyakinan, pendeklarasian keyakinan, dan refleksi keyakinan muncul dalam sejarah ketiga agama tersebut. Konstelasi itu dipahami sebagai satu kesatuan dan mempunyai pusat yang sama. Dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam sejarah perubahan besar ini benar-benar dramatis. Dalam merespons tantangan baru dan besar di sejarah dunia, komunitas keyakinan (dalam agama Kristen dan Islam),yang awalnya kecil kemudian tumbuh berkembang menjadi besar dan mengalami beberapa rangkaian perubahan keagamaan. Saya mempelajari konsep ini dari sejarawan ilmu pengetahuan Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “Struktur Revolusi Ilmiah” (1962): Apa yang berubah di Revolusi Copernican? Bulan, matahari, bintang tetap sama. Tapi kita yang berubah: cara kita memandang mereka, cara kita memandang dunia. Paradigmanya: Seluruh konstelasi keyakinan, nilai, teknik, dan lain sebagainya, diterapkan oleh komunitas keyakinan yang sama.” Awalnya saya mengaplikasikan teori paradigma pada gereja lalu kemudian ke agama-agama lainnya. Apa yang berubah pada Reformasi? Tuhan, Yesus Kristus, atau Roh Kudus tetaplah sama. Yang berubah adalah pandangan dari pemeluknya: paradigma, modelnya.
Analisa historis tentang paradigma agama diperuntukkan untuk pengetahuan. Analisa paradigma memudahkan transformasi struktur sejarah: dengan memusatkan perhatian pada dasar dan variabel yang kukuh pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, perubahan- perubahan besar di sejarah dunia dan perubahan-perubahan besar dalam suatu agama akan dapat dengan mudah dijelaskan.
Jadi sistematis sejarah tentang analisa konstelasi perubahan secara keseluruhan harus disepakati. Dalam buku saya, Agama Kristen,saya membahas tentang paradigma makro dalam sejarah
A. Agama Kristen (bandingkan diagram): Sekarang saya membahas
tentang garis besar diagram:
-
paradigma kehancuran agama Yahudi di awal munculnya agama Kristen;
-
Paradigma Hellenistic tentang penyatuan cabang-cabang Gereja Kristen pada jaman dulu;
-
Paradigma Katolik Roma jaman abad pertengahan;
-
Paradigma Protestan tentang Reformasi;
-
Paradigmaorientasimoderntentangalasandanperkembangan;
-
Paradigma penyatuan cabang-cabang Gereja Kristen tentang postmodern?
Hans Kung: Situasi Keagamaan Sekarang
Judaism, London (SCM Press) 1992; New York (Crossroad) 1992.
Christianity, It’s Essense and History, London (SCM Press) 1995;
New York (Continuum) 1995
Islam, London (One World) 2006 (in preparation)
Pemahaman Pertama (Lihat Diagram 01): Setiap agama tidak berdiri sendiri-sendiri dan tidak berubah. Sebaliknya, agama berubah dan terkadang perubahan itu membingungkan dan membuat kekacauan. Pemahaman pertama adalah paradigma itu dapat berlaku hingga masa kini dan itu sangat bermanfaat bagi Yahudi dan Islam. Dalam diagram digambarkan dengan garis sambung (tidak putus-putus). Sebaliknya, paradigma lama atau ilmu pengetahuan “yang sebenarnya”( misalnya Ptolemy) dapat secara empiris disanggah atau dibenarkan dengan bantuan ilmu matematika dan percobaan-percobaan. Tapi dalam bidang agama (dan juga seni), segala sesuatunya berbeda: pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keyakinan, moral dan ritual (misalnya antara Roma dan Gereja Timur atau antara Roma dan Luther) tidak bisa dijawab dengan matematika atau percobaan-percobaan. Paradigma- paradigma lama dapat berjalan selaras dengan paradigma-paradigma baru.
B. Sama halnya dalam agama Yahudi, saya juga membahas tentang
paradigma makro dalam sejarah agama Yahudi (bandingkan diagram):
-
Paradigma kesukuan sebelum terbentuknya suatu negara;
-
Paradigma kerajaan: periode monarki;
-
Paradigma pemimpin agama
-
Paradigma jaman pertengahan: pendeta Yahudi dan sinagoge
-
Paradigma modern: Asimilasi
-
Paradigma penyatuan tentang postmodern?
Pemahaman Kedua (Lihat Diagram 02): Adanya paradigma- paradigma yang ada berikut dengan perbedaan-perbedaan mereka sangatlah penting untuk menilai situasi suatu agama. Ini adalah pemahama kedua. Mengapa? Sekarang ini orang-orang yang beragama sama hidup di dalam paradigma yang berbeda. Mereka dibentuk oleh kondisi-kondisi dasar dan masalah-masalah mekanisme historis. Misalnya, penganut Katolik yang menerapkan hidup spiritual di abad ketiga belas. Ada pula beberapa perwakilan Orthodox Timur yang juga menerapkan hidup spiritual di abad keempat/kelima. Dan untuk beberapa pengikut Protestan mereka hidup biasa, tidak sealim penganut Kristen Katolik.
Keberadaan paradigma-paradigma itu menjelaskan pada kita bahwa dalam agama Yahudi dan Islam orang-orang hidup dalam paradigma yang berbeda-beda.
Hal itu sama halnya dengan keinginan orang Arab yang masih bermimpi tentang bersatunya orang Arab dalam satu bangsa Arab yang besar (Pan-Arabisme). Sedangkan orang lain lebih ingin melihat orang Arab menjadi satu ikatan, bukan dalam keAraban mereka tapi dalam Islam (Pan-Islamisme). Beberapa penganut Yahudi Ulta-Ortodox melihat keidealan agama mereka di agama Yahudi abad pertengahan dan menolak Israel. Sebaliknya banyak kaum Zionis berusaha keras mewujudkan kerajaan David dan Solomon yang hanya berdiri beberapa dekade saja.
C. Dalam buku saya tentang Islam yang akan diterbitkan pada bulan
Oktober 2006 oleh penerbit Oneworld, Oxford. Saya juga menjelas-
kan paradigma makro dalam sejarah Islam (bandingkan diagram):
-
paradigma komunitas Islam orisinil;
-
paradigma kerajaan Arab;
-
paradigma klasik Islam sebagai agama dunia;
-
paradigma Islam tentang modernisasi
-
paradigma penyatuan tentang postmodern?
Pemahaman ketiga (Lihat Diagram 03): Tampaknya adanya para- digma-paradigma baru inilah yang menjadi sumber konflik dalam agama dan antaragama. Juga menjadi penyebab adanya perbedaan trend, ketegangan, perselisihan dan perang. Pemahaman ketiga yang muncul adalah, untuk agama Yahudi, Kristen, dan Islam pertanyaan utamanya adalah: bagaimana reaksi-reaksi agama itu terhadap Jaman Pertengahan (setidaknya agama Kristen dan Islam memandang Jaman Pertengahan itu sebagai jaman keemasan). Dan bagaimana reaksi agama-agama itu terhadap modernisasi? Setelah Reformasi, agama Kristen harus mengalami pergeseran paradigma, yaitu Pencerahan. Agama Yahudi mengalami Pencerahan setelah Revolusi Prancis dan Napoleon. Dan konsekuensinya, agama Yahudi juga mengalami reformasi agama. Namun Islam tidak mengalami reformasi agama. Oleh karenanya Islam juga mengalami masalah menghadapi modernisasi berikut komponen-komponennya: kebebasan beragama, hak asasi manusia, toleransi, dan demokrasi.
Tantangan-tantangan Masa Kini
Mungkin Anda pernah mengalami hal ini sebelumnya:
Banyak penganut Yahudi, Kristen, dan Islam yang memahami konten paradigma modern dapat bergaul dengan baik dengan penganut agama lain dibandingkan dengan penganut yang seagama namun berpahaman pada konten paradigma yang berbeda. Sebaliknya, penganut Katolik Roma yang hidup di Abad Pertengahan dapat memahami moralitas seksual dengan elemen “pertengahan” agama Islam dan Yahudi (seperti yang diungkapkan di konferensi PBB di Kairo pada tahun 1994 tentang populasi).
Mereka yang menginginkan rekonsiliasi dan perdamaian tidak akan bisa menghindari paradigma analisa kritik-diri. Oleh karenanya mungkin untuk menjawab pertanyaan seperti ini: Di manakah dalam sejarah agama Kristen (ataupun agama-agama lainnya) yang tidak berubah dan yang berubah, di manakah kontinuitas dan diskontinuitas, yang setuju atau yang tidak setuju? Ini adalah pemahaman keempat. Yang harus dilindungi adalah inti, pusat, dan dasar dari suatu agama. Kepercayaan yang teguh kepada semangat Kristus, hukum pem- bujangan: variabel. Yang tidak harus dilindungi adalah segala sesuatu yang sejak awal dipandang tidak penting. Semua variabel-variabel dapat dihilangkan (atau sebaliknya dapat dikembangkan) jika memang diperlukan.
Jadi demi mengatasi kebingungan tentang masalah keagamaan, khususnya di era globalisasi, dibutuhkan analisa paradigma untuk menghadapi orientasi global. Sering kali kita dibingungkan dengan perwujudan hubungan internasional, hubungan antara Barat dan Islam, dan juga hubungan antara agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sini pilihannya jelas: perang antaragama, perselisihan peradaban, perang antarbangsa atau dialog yang mengarah pada perdamaian antarbangsa- bangsa. Menghadapi ancaman bagi seluruh umat manusia, daripada membangun kebencian dan menyebarkan hawa balas dendam, alangkah baiknya jika kita merobohkan dinding prasangka dan membangun jembatan dialog khusus yang benar-benar mengarah pada Islam.
Kontribusi Tiga Agama untuk Etika Global
Sangatlah penting untuk membangun jembatan dialog untuk menjembatani ketiga agama tersebut. Karena manusia berkembang mulai dari wujud binatang sampai menjadi manusia. Manusia juga belajar bagaimana berperilaku peri kemanusiaan dan bukan berperilaku sebaliknya. Namun demikian manusia tidak dapat lepas dari dorongan nafsunya, yang menampakkan diri mereka sebagai binatang buas. Dan mereka terus berjuang untuk mewujudkan diri mereka sebagai manusia, bukan binatang.
Oleh karena itu di setiap agama, terdapat perintah filosofis dan ideologis yang masih berlaku hingga saat ini:
- “Kamu tidak boleh membunuh—atau menyiksa,menyakiti, memer- kosa”, atau istilah positifnya adalah: “Hormatilah hidup orang lain”. Itu adalah komitmen pada anti kekerasan dan menghormati segala bentuk kehidupan.
- “Kamu tidak boleh mencuri—atau mengeksploitasi, menyuap, ko- rupsi atau istilah positifnya adalah: Buatlah kesepakatan yang jujur dan adil.” Ini adalah komitmen pada solidaritas keteraturan ekonomi dan .
- “Kamu tidak boleh berbohong—atau menipu, memalsu, memani- pulasi”, atau istilah positifnya adalah: “Berbicara dan bertindaklah dengan jujur.” Ini adalah komitmen pada toleransi dan kejujuran.
- Dan akhirnya,”Kamu tidak boleh melakukan kekerasan seksual, memalukan atau merendahkan pasangan hidupmu” atau istilah positifnya adalah: “Hormatilah dan cintailah satu sama lain”. Ini adalah komitmen pada persamaan hak dan hubungan antara pria dan wanita.
Empat etika yang ditemukan di Patanjali, penemu Yoga, atau di Kitab agama Buddha, Kitab Injil Yahudi, Kitab Perjanjian Baru dan Kitab Al- Qur’an, berdasarkan pada dua prinsip dasar etika:
- Pertama-tama adalah Golden Rule (Peraturan Wajib) yang dikatakan beberapa abad sebelum Masehi oleh Konfusius dan dikenal di seluruh agama-agama besar: “Jangan melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain pada Anda.” Meskipun peraturan ini sederhana, tapi sangat membantu untuk mengambil keputusan di saat-saat yang sulit.
- Golden Rule itu didukung oleh peraturan kemanusiaan, yang sama sekali tidak diulang-ulang dengan cara yang berbeda: “Setiap manusia, baik itu tua maupun muda, lelaki atau wanita, normal atau cacat, Kristen, Yahudi atau Muslim harus memperlakukan sesamanya dengan cara berperikemanusiaan, bukan sebaliknya.” Kemanusiaan tidak dapat dibagi.
Jadi jelaslah bahwa etika global bukan berarti harus menjadi sistem etika seperti sistem etika Aristotle, Thomas Aquinas atau Kant (“etika”). Tapi etika global menjadi nilai-nilai, kriteria, dan sikap dasar etika yang membentuk keyakinan moral pribadi manusia dan lingkungannya.
Tentu saja etika ini bertentangan dengan fakta: perintah kema- nusiaan tidak dipenuhi tapi harus diingat sepanjang waktu. Tapi, seperti yang diungkapkan Kofi Annan dalam Perkuliahan tentang Etika Global di Tubingen pada tahun 2003: “Tapi jika menyalahkan suatu agama karena kesalahan tindakan atau perkataan penganutnya itu salah, maka menganggap nilai-nilai tertentu sebagai nilai universal hanya karena beberapa kelompok orang tidak dapat menerimanya dengan lapang dada itu juga suatu kesalahan.”
Saya akan membuat kesimpulan seperti kesimpulan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam pidatonya: “Apakah kita masih mempunyai nilai-nilai universal? Ya, kita masih mempunyai nilai-nilai universal, tapi sebaiknya kita tidak mengabaikan nilai-nilai universal itu begitu saja.
- ・Nilai-nilai universal itu harus dipikirkan
- ・Nilai-nilai universal itu harus dibela
- ・Nilai-nilai universal itu harus diperkuat”
Dan dalam diri kita sendiri kita harus menemukan keinginan untuk menjalani kehidupan berdasarkan pada nilai-nilai yang kita nyatakan sebagai nilai universal, baik itu kehidupan pribadi kita, kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga kehidupan kita di dunia.
KEKRISTENAN SEBAGAI FAKTOR
DALAM POLITIK GLOBAL
Makalah Dipresentasikan oleh
Profesor Hans Kung
Profesor Emeritus, Universitas Tubingen, Mei 2007
TERDAPAT lebih dari satu agama Kristen, sama halnya terdapat lebih dari satu agama Yahudi dan lebih dari satu agama Islam. “Agama Kristen” yang berbeda berasal dari konstelasi sejarah yang berbeda. Konstelasi sejarah tersebut mempunyai bentuk dan efek politik yang berbeda pula: Katolik Roma, Ortodoks, Kristen Reformasi. Tapi agama Kristen pada khususnya harus dilihat dari konteks agama lain karena ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan untuk semuanya.
Pernyataan awal tentang agama sebagai faktor di politik global
1. Agama dan Takhyul harus dibedakan:
- Kritik yang dilontarkan oleh Marxist tentang agama telah membedakan agama dengan takhayul. Namun, agama tidak dikenal sebagai otoritas mutlak untuk segala sesuatu yang relatif, kondisional dan otoritas untuk manusia. Tetapi otoritas itu diperuntukkan untuk Kemutlakan itu sendiri, atau tradisi kita menyebutnya sebagai “Tuhan”. Tuhan itu disembah tidak hanya oleh kaum Yahudi dan Kristen tapi juga oleh Muslim. Umat Hindu menyebut Tuhan dengan nama Brahman, umat Hindu menyebut dengan Tuhan, dan orang Cina menyebutnya dengan Heaven atau Dao. Segenap penganut agama-agama tersebut menyebut Tuhan dengan konsep mereka sendiri-sendiri.
- Sebaliknya, takhayul disebut sebagai otoritas mutlak untuk sesuatu yang relatif dan tidak mutlak. Takhayul mendewakan benda-benda (uang, kekuatan, dan sex). Atau juga mendewakan orang (Stalin, Hitler, Mao, Pemimpin Negara dan juga Paus). Takhayul juga mendewakan organisasi manusia (Partai dan Gereja). Oleh karena itu pendewaan terhadap seseorang juga merupakan bentuk dari takhayul! Namun tidak semua takhayul itu agama karena terdapat pula bentuk takhayul yang modern. Sebaliknya tidak semua agama itu takhayul; karena ada agama yang benar-benar merupakan suatu agama. Tapi agama apa pun dapat berubah menjadi takhayul jika agama itu menjadikan sesuatu yang tidak penting menjadi penting, atau mengubah sesuatu yang relatif menjadi sesuatu yang mutlak.
2. Kebebasan Beragama Dimiliki oleh Yang Yakin terhadap
Agama dan Yang tidak Yakin terhadap Agama:
- Tidak seorang pun baik secara fisik maupun moral dipaksa untuk menerima agama atau ideologi tertentu. Setiap orang harus diizinkan untuk meninggalkan atau berpindah agama. Artikel 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjelaskan hal itu. Kebebasan untuk penganut ateis tidak selalu ada: tapi ateis harus tetap diberikan kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan berpropaganda bahkan di negara yang berlandaskan pada agama. Dan kebebasan untuk pemeluk suatu agama pun juga tidak selalu ada: tapi penganut-penganut suatu agama harus tetap diberikan kebebasan berpikir, berpendapat dan berpropaganda di semua negara baik itu negara yang sekuler, sosialis, Islam atau orientasi- orientasi yang lain.
3. Agama apa pun dapat disalahgunakan dan dieksploitasi secara politik:
- Pada masa sekarang ini agama muncul sebagai agen politik global. Memang benar adanya bahwa agama sering kali menunjukkan sisi perusakan dalam sejarah. Agama-agama telah menstimulasi dan melegitimasi kebencian, kekerasan dan perang. Tapi dalam banyak kasus agama-agama itu juga menstimulasi dan melegitimasi pemahaman, rekonsiliasi, kolaborasi dan perdamaian. Dalam bukunya tentang potensi agama demi mewujudkan perdamaian, Dr. Markus Weingardt telah menginvestigasi enam studi kasus dan lebih dari tiga puluh contoh mediasi konflik berbasiskan pada agama. Dan pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1990an, Dr. Gunther Gebhardt menekankan pentingnya pendidikan untuk mewujudkan perdamaian dalam gerakan perdamaian keagamaan. Pada dekade belakangan ini, di segenap penjuru dunia sedang digalakkan dialog antaragama dan kolaborasi antaragama pun juga telah berkembang. Dalam dialog- dialog tersebut tokoh-tokoh masing-masing agama menengarai bahwa pernyataan-pernyataan etika dasar mereka mendukung dan memperdalam nilai etika sekuler yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1993 di Parlemen Agama Dunia di Chicago, terdapat lebih dari dua ratus perwakilan dari seluruh agama di dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mendeklarasikan konsensus mereka yang berdasarkan pada nilai etika, standar, dan sikap yang telah disepakati sebagai dasar untuk etika global.
4. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam Dipandang Sebagai Agama
yang Erat Kaitannya dengan Kekerasan:
- Agama Yahudi, Kristen, dan Islam dipandang sebagai agama yang erat kaitannya dengan kekerasan karena ketiganya adalah agama “monotheistic”. Berbeda halnya dengan agama Buddha sebagai agama “non-theistic”. Mungkinkah itu karena dalam masing-masing agama sudah terdapat nilai-nilai kekerasan, karena ikatan mereka hanya kepada satu Tuhan, karena agama monotheis itu tidak toleran dan siap kapan pun melakukan kekerasan?
- Tapi kita harus mencatat bahwasanya agama ada sejak diciptakannya manusia. Dan kekerasan ada sejak manusia dicipta- kan. Dari generasi ke generasi manusia selalu menguji norma- norma etika untuk membuktikan bahwasanya mereka menentang kekerasan.
- Namun perkembangan jaman dan agama telah melegitimasi perang yang disebut sebagai “perang suci” yang dilakukan oleh sekelompok misionaris yang mengatasnamakan dewa. Apakah perang itu atas nama satu Tuhan atau lebih dari satu Tuhan tidaklah penting. Tentu saja akan salah kaprah jika mengatakan bahwa semua perang yang dilakukan oleh umat Kristen berlandaskan pada motivasi agama. Ketika penjajah kulit putih di Amerika Selatan dan Amerika Utara dan di Australia membunuh ribuan suku Indian dan Aborigin, ketika penjajah Jerman membunuh ratusan Hereros, ketika tentara Inggris menembaki demonstran-demonstran India, tentara Israel di Lebanon dan Palestina membunuh ratusan rakyat sipil, atau pasukan Turki yang membunuh ratusan rakyat Armenia, maka tindakan-tindakan itu tidak dapat disebut sebagai percaya pada satu Tuhan atau tidak pula dapat disebut sebagai Perang Dunia kedua.
5. Masing-masing Agama harus Mencerminkan Tradisi Keagamaannya:
- Pada saat manusia dapat menghancurkan peradaban mereka sendiri dengan menggunakan teknologi, semua agama khususnya agama Yahudi, Kristen, dan Islam yang sering kali agresif harus benar-benar menghindari perang dan menyebarkan perdamaian. Maka di sini perbedaan arti masing-masing tradisi pun tidak dapat dihindari. Ada dua hal yang mendasari:
- Pertama: Kata-kata dan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada peperangan dalam tradisi seseorang harus diinterpretasikan berdasarkan pada sejarah dan situasi pada saat itu tanpa membuat pengecualian. Itu berlaku bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam:
-
- ・“Perang Yahweh” yang kejam dan pernyataan penuh dendam di Kitab Injil Yahudi dapat dipahami melalui situasi dibuatnya pernyataan tersebut dan dari situasi pembelaan diri melawan musuh-musuh yang superior.
-
- ・Pengabar Injil dan “pejuang-pejuang perang” dihukum karena membela ideologi gereja di Awal dan Abad Pertengahan.
-
- ・Panggilan untuk berperang di Al-Qur’an menggambarkan situasi nyata Nabi Muhammad Saw. di Madinah dan karakter surat-surat yang diturunkan di Madinah. Panggilan berperang melawan politeistik Mekkah tidak dapat diartikan sebagai membenarkan penggunaan kekerasan secara prinsipil.
- Kedua: kata-kata dan berbagai tindakan yang mampu menciptakan perdamaian di setiap tradisi harus dicermati dengan seksama agar bisa menjadi dorongan positif di masa kini. Prinsip- prinsip etika berikut dalam konteks perang serta perdamaian harus diperhatikan untuk membantu mewujudkan ketertiban dunia.
-
- ・Perang-perang di abad 21 juga tidak suci, adil ataupun bersih. Mengingat begitu banyaknya korban jiwa manusia, begitu besarnya kerugian sarana prasarana, warisan budaya, serta kerusakan ekologi lingkungan, bahkan perang-perang modern juga tidak bertanggung jawab, misalnya ‘perang Yahweh’ (Sharon), ‘perang Salib’ (Bush), dan ‘Jihad’ (al-Qaida).
-
- ・Perang bukanlah sebuah priori yang tidak bisa dihindari: diplomasi yang lebih terkoordinasi, didukung oleh kontrol senjata yang efisien pasti bisa menghindarkan perang di Yugoslavia serta kedua Perang Teluk.
-
- ・Kebijakan yang tidak etis tentang berbagai kepentingan nasional—misalnya tentang cadangan minyak atau tentang hegemoni negara-negara Timur Tengah—berimbas pada ting- kat kompleksitas perang.
-
- ・Pasifisme absolut, di mana perdamaian adalah tujuan ter- tinggi, sehingga segalanya harus dikorbankan, secara politis tidak mungkin bisa terwujud dan bahkan tidak bisa dipertang- gungjawabkan sebagai prinsip politik. Hak untuk membela diri secara tersurat telah ditegaskan dalam Pasal 51 di Piagam PBB. Dengan kata lain, perdamaian dengan harga apa pun, katakanlah jika ada ancaman Holocaust atau genosida baru, adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Diktator megalomania serta pembunuh massal (seperti Stalin dan Hitler) harus dilawan.
-
- ・Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dipertang- gungjawabkan di hadapan Mahkamah Internasional, dan diharapkan administrasi Amerika, seperti yang diterapkan di era George W. Bush, pada akhirnya akan mendukung sesuai tradisi terbaik Amerika.
- Berikutnya, saya akan membahas secara spesifik berbagai peran dari Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja-Gereja Protestan dalam dunia politik.
Gereja Katolik Roma sebagai Sebuah Faktor Politik
Pandangan Roma tentang Kristianitas (yang umumnya dirujuk sebagai pandangan Katolik) sudah dipersiapkan sejak abad ke-empat/ lima, secara teologi oleh Augustine, dan secara politis oleh para Paus Roma, setelah kekaisaran dikuasai oleh Konstantinopel. Baru di abad ke-11, kebijakan tersebut diterapkan oleh para Paus dalam Reformasi Gregorian (Paradigma III), dengan menggunakan pemalsuan Pseudo- Isidoran. Yang menjadi tonggak utama visi Roma ini adalah Uskup Roma dan Paus, yang, dengan mengatasnamakan Tuhan dan Yesus Kristus, menyatakan hak universal dan absolut untuk memimpin gereja (dan selama beberapa waktu menyatakan berhak untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan): keduanya dianggap memiliki kompetensi normatif untuk menginterpretasikan doktrin dan otoritas legislatif, eksekutif, serta yudisial dalam berbagai segi kehidupan gereja.
Bahkan sejak abad ke-11, pernyataan hak kekuasaan absolut ini (dan tentunya dibarengi dengan faktor-faktor lain) telah memunculkan adanya konflik (misalnya ‘Kontroversi Pelantikan’) dengan kekaisaran Jerman, serta menjadikan terpecahnya gereja Latin di Barat dengan Gereja Ortodoks di Timur; kemudian di abad ke-16 memunculkan perpecahan gereja di Barat menjadi gereja Reformasi dan gereja Kontra-Reformasi; dan akhirnya, pada abad 19/20, memunculkan adanya polarisasi, hingga pengucilan. Dan memang, konflik hierarki yang berorientasi pada Roma dan para pengikut Katolik serta pendeta Kristen ini, semuanya telah tercermin dalam teologi.
Di paruh kedua abad 20, Dewan Vatikan Kedua dalam praktiknya mengadopsi berbagai isu utama baik dalam Reformasi (P IV) maupun modernitas (P V), akan tetapi berbagai kompromi dan tindakan setengah hati yang lakukan oleh Kuria Romawi dalam berbagai bidang menjadi alasan tidak terwujudnya visi Gereja Katolik yang konsisten di abad ke-20. Masalah kolegial antara Paus dan Uskup yang diputuskan di tahun 1965 sebagai penyeimbang dari definisi Uskup Agung oleh Dewan Vatikan Pertama (1870) diacuhkan oleh Kuria Romawi setelah Dewan Vatikan Kedua dan absolutisme ke-Paus-an kembali dikukuhkan dan diagung-agungkan dengan bantuan media masa.
Hampir di seluruh dunia, Gereja Katolik tetap menjadi kekuatan spiritual, dan merupakan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan tidak bisa dibasmi oleh Nazi-isme, Stalin-isme, dan Mao-isme. Terpisah dari besarnya organisasi ini, di berbagai belahan dunia, ia juga memiliki basis yang unik dalam hal keluasannya, baik berupa komunitas, rumah sakit, sekolah, serta lembaga-lembaga sosial, di mana berbagai aktivitas kebaikan yang tak terhingga jumlahnya berhasil dilaksanakan tak peduli besarnya kesulitan yang menghadang; di mana banyak pastur mendedikasikan hidupnya untuk membantu para jemaatnya baik pria maupun wanita, di mana tak terhitung jumlah penganut yang mengabdikan diri membantu anak-anak, orang tua, serta orang- orang miskin dan kurang beruntung lain. Ini merupakan komunitas dunia dari penganut Katolik yang memiliki komitmen tinggi. Dan komitmen tersebut selalu terbukti efektif secara politis: dalam banyak situasi penindasan dan ketidakadilan, adalah komitmen para penganut Kristen taat yang memungkinkan terjadinya perubahan—yang kadang harus mereka bayar dengan nyawa. Berbagai kelompok serta individu penganut Katolik memainkan peran penting dalam menggulingkan kediktatoran di Amerika Selatan dan Filipina.
Akan tetapi, sejarah Gereja Katolik, seperti halnya institusi- institusi lain, juga bersifat ambivalen. Kita semua tahu bahwa dibalik sebuah organisasi yang efisien, seringnya terdapat alat kekuasaan dan keuangan yang dioperasikan dengan cara-cara yang duniawi. Dibalik statistika yang hebat, dan berbagai peristiwa dan tata ibadah megah yang melibatkan sejumlah besar penganut Katolik, seringnya hal ini dibarengi dengan tradisi Kristen yang dangkal dengan substansi yang buruk. Kerap kali, seperangkat fungsionaris yang selalu mendambakan posisi di Roma, yang patuh kepada ‘atasan’ tapi sewenang-wenang kepada pihak ‘di bawah’-nya, menemukan jalan menuju hierarki yang lebih tinggi. Sebuah teologi ilmiah yang mana sejarah telah mencatatnya sebagai authoritarian dan tidak berdasarkan injil umumnya ditemukan dalam sebuah sistem tertutup yang bersifat doktrin dan dogmatis. Selain itu, kesuksesan budaya Barat yang sering dielu-elukan secara berlebihan ini selalu diiringi dengan sekularisasi dan penyimpangan dari tugas- tugas spiritual yang seharusnya.
Pelayanan pastoral Uskup Roma ke gereja-gereja bisa berhasil dan berarti jika ia dilakukan dengan tanpa pamrih, seperti yang dicontohkan oleh rasul Peter. Sehingga tidak akan ada yang mempermasalahkan fakta bahwa ke-Paus-an telah bekerja keras untuk mempertahankan kekuatan, kesatuan dan kebebasan dari, setidaknya, gereja-gereja di Barat. Sistem Roma juga telah terbukti lebih efisien dari pada sistem aliansi gereja dari gereja-gereja di Timur. Hingga saat ini, jika Paus memiliki kredibilitas, ia akan bisa berbicara hingga menyentuh hati nurani seluruh manusia di dunia sebagai otoritas moral. Akan tetapi peran spiritual politis ganda dari Vatikan sebagai pemerintah gereja dan sebagai negara yang berkedaulatan sangat bersifat ambivalen. Gabungan yang bersifat merusak dari keduanya terlihat jelas saat Vatikan berusaha menjadikan ide-ide moralnya sebagai kebijakan, misalnya dalam menghadapi isu seperti AIDS atau kontrol kelahiran. Konferensi Populasi Dunia di Kairo tahun 1994 bisa menjadi salah satu contohnya.
Dengan kata lain, kelemahan dan cacat dalam sistem Roma sudah jelas, dan hal ini sangat membatasi pengaruh Paus, bahkan dalam ‘ranah kekuasaannya’ sendiri. Telah banyak penganut Katolik yang mempertanyakan klaim kekuasaan Roma, mereka menyatakan bahwa sekali lagi sistem Roma menyimpang dari tugas dan perintah utama Kristen dan gereja. Sejak Abad Pertengahan, sisi negatif tersebut telah jelas terlihat. Sejak saat itu, telah ada berbagai keluhan mengenai:
- Sikap otoriter dan tak pernah salah dalam hal dogma dan moralitas
- Pembebanan terhadap kaum awam, pendeta dan gereja-gereja lokal, hingga ke hal-hal kecil yang sangat rinci
- Keseluruhan kekuasaan absolut yang telah ter-fosilisasi, yang lebih berorientasi pada kekaisaran Roma dari pada rasul Peter, seorang nelayan sederhana dari Galilee.
Oportunitas Gereja Katolik: dari perspektif Roma, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat gereja-gereja yang rapuh dibalik megahnya wajah Gereja Katolik. Jutaan penganut Katolik yang berkumpul di gereja di berbagai kesempatan bisa memberikan kesan yang sangat bisa menipu tentang kekuatan keyakinan dalam diri yang menyatukan gereja-gereja Katolik sebagai kesatuan multinasional berbasis agama yang signifikan di dunia. Di Roma sendiri, terdapat pemikiran bahwa reformasi dalam gereja yang didambakan oleh banyak pihak tidak akan mampu memajukan Gereja Katolik menjadi lebih baik dari pada gereja- gereja Protestan, yang mana semua telah memenuhi tuntutan reformasi ini tapi tidak menunjukkan hasil yang lebih baik. Alih-alih, gereja lebih memilih untuk berkembang berdasarkan inti kehidupan positif yang ia miliki, di mana pendorong terbesarnya merupakan kekuatan diri yang didapatkan dengan cara melihat kepada Tuhan dan menjumpai Yesus Kristus.
Dari perspektif ekumenis (umum), hanya masalah waktu untuk melihat pentingnya menegaskan perlunya agar gereja lebih fokus pada hakikat Kristianitas—Tuhan dan Yesus Kristus. Akan tetapi Karena kampanye ajaran-ajaran injil yang diawali oleh John Paul II beberapa dekade lalu diwarnai oleh isu-isu dogmatis dan tuntutan moral lama, serta dalam praktiknya merupakan kampanye peng-Katolik-an ulang, ia telah gagal: meski telah didukung dengan ribuan dokumen, pidato, dan propaganda media besar-besaran, Paus tidak berhasil meyakinkan mayoritas penganut Katolik tentang pandangannya akan berbagai pertanyaan yang tengah diperdebatkan, khususnya tentang moralitas yang berhubungan dengan seksualitas (kontrasepsi, hubungan seksual pranikah, dan aborsi).
Dalam hal ini, harus ada peringatan agar tidak muncul harapan palsu: para penganut yang pergi ke berbagai even di gereja seharusnya tidak menutupi fakta bahwa di sini, tidak hanya banyak orang yang penasaran dan tengah mencari makna hidup, akan tetapi lebih dari itu, mereka berasal dari penganut Katolik tradisional. Orang-orang muda yang datang kebanyakan berasal dari kaum konservatif ‘movimenti’ yang berasal dari Spanyol, Italia dan Polandia, yang sangat khas akan sifat pemujaan mereka terhadap Paus, dan bukan untuk mengikuti perintah- perintah moral atau untuk menunjukkan komitmen mereka yang tinggi terhadap komunitas gereja di tempat asal mereka. Meskipun telah didoktrin selama beberapa dekade, hanya terdapat minoritas penganut, bahkan dari kalangan mereka, yang mengikuti larangan penggunaan pil dan kondom. Angka aborsi juga tinggi, terutama di negara-negara di mana gereja telah melarang penggunaan pil.
Dogma Helenis-Yunani tradisional dari abad ke-empat/lima, seperti dogma Kontra-Reformasi di abad ke-16, hampir tidak diketahui oleh orang-orang Katolik awam. Terlebih, empat dogma Vatikan yang baru—Konsepsi Tanpa-Cela (1854) dan Asumsi (1870) Maria, Keutamaan yuridiksi dan infalibilitas (sifat tidak pernah salah) ke- Paus-an (1870) juga umumnya diacuhkan, atau dipertanyakan, bahkan di Gereja Katolik. Sehingga, emigrasi besar-besaran dari Gereja Katolik terjadi, khususnya di negara-negara asal Katolik. Terlebih, karena adanya penolakan pernikahan bagi pendeta dan penahbisan pendeta perempuan, dan karena sistem Roma yang otoriter, dalam waktu dekat separuh dari paroki-paroki yang ada di dunia tidak akan lagi memiliki pastur, dan rumah pastur yang telah dibangun selama berabad-abad akan runtuh. Di Amerika Latin, jutaan penganut Katolik telah beremigrasi ke gereja Pantekosta (tidak semua gereja ini dianggap sebagai ‘sekte’) karena mereka telah menemukan pendeta yang menginspirasi dan komunitas yang siap mengabdi di sana.
Kelemahan fundamental dari sistem Roma ini, yang harus dibedakan dari Gereja Katolik, menjadikan rekonsiliasi dengan Gereja
Ortodoks di Timur dan gereja-gereja Reformasi menjadi sulit.
Gereja Ortodok di Timur sebagai Sebuah Faktor Politik
Tak diragukan lagi, Gereja Ortodoks di Timur lebih dekat dengan Kristianitas dalam berbagai aspek. Pondasi paradigma Helenis-Yunani dari gereja Roma kuno (II) sudah ditanamkan oleh rasul Paul selepas paradigma Kristen-Yahudi (I). Gereja awal ini masih belum memiliki pemerintahan terpusat seperti Gereja Katolik Roma di Barat (III). Gereja ini mengizinkan pendeta untuk menikah, meskipun hal ini tidak berlaku bagi para uskup, sehingga keuskupan umumnya berangkat dari perintah biara. Di Gereja Ortodoks, para penganut setia juga menerima Ekaristi dalam dua bentuk, roti dan anggur. Dan Gereja Ortodoks juga telah bertahan melalui berbagai sistem politik, bahkan selama penindasan terakhir di Rusia di bawah rezim Komunis selama tujuh puluh tahun yang memakan ribuan martir. Hal ini dikarenakan tata ibadah serta lagu-lagu himne-nya yang sangat indah yang semuanya akan menyita perhatian bahkan mereka yang berasal dari Barat.
Akan tetapi, kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa perbedaan gereja ortodoks dari kristianitas awal juga sangat jauh. Penganut awam Kristen ortodoks masih sulit membedakan antara tata ibadah perjamuan terakhir Yesus di Byzantin dan di Rusia. Salah satu sisi bahaya gereja Ortodoks ada pada kenyataan bahwa ia merupakan gereja negara, di mana di bawah kaisar, Tsar, atau sekretaris jenderal, gereja bisa menjadi alat negara atau partai. Model simfoni dari negara atau gereja yang muncul di Byzantium jelas menunjukkan ketergantungan Gereja Ortodoks Rusia pada rezim politik masa itu, sebuah ketergantungan yang bahkan masih terlihat hingga saat ini, yang merupakan sebuah tradisi suci kuno. Ia tidak hanya senada dengan gereja negara Muscovite yang dibentuk pada abad ke-15/16, ia juga memiliki akar yang dalam dalam tradisi Byzantium, yang telah ada sejak Kaisar Konstantinopel setelah perubahan Kristianitas di abad ke-empat. Tradisi Byzantin- Slavonic gereja-negara juga menjelaskan mengapa kebanyakan gereja ortodoks tidak percaya akan ide-ide yang muncul tahun 1789an, ide-ide demokrasi, perpisahan antara gereja dan negara, kebebasan berpikir dan beragama, dan lain-lain.
Bahaya ini sangat terlihat dalam nasionalisme modern. Bagi para pengikut di masa pemerintahan Ottoman, selama berabad-abad gereja membentuk kubu pertahanan untuk membentengi memori akan identitas dan kemerdekaan mereka, sehingga gereja memiliki fungsi konstitusi dan legitimasi dari negara. Akan tetapi dalam sejarah Ortodoks baru, ideologi nasionalis yang muncul seringnya malah menjadi penyulut persaingan antaretnik dan bukannya malah meredakan dan menjaganya agar tetap terkontrol. Perkembangan-perkembangan yang muncul di Yugoslavia dulu diduga kuat menerapkan dimensi fanatik tersebut karena selama berabad-abad gereja-gereja di sana telah menanamkan nasionalisme dan bukannya meredakannya: Gereja Katolik mendorong nasionalisme Kroasia, Gereja Ortodoks mendorong nasionalisme Serbia. Tentunya nasionalisme juga muncul di Polandia, Irlandia, dan di berbagai negara Protestan lain. Akan tetapi jika memang ada dorongan dan bahaya dari dunia Ortodoks, sifatnya tidak sekuat otoritarianisme (Katolik Roma) atau subyektivisme (Protestan modern), seperti yang terjadi di Barat, dari pada nasionalisme!
Oportunitas Gereja Ortodoks Timur: dari perspektif Roma, gereja- gereja di timur memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dari Gereja Katolik Roma. Karena kesamaan masa lalu mereka di milenium pertama, keduanya memiliki struktur yang sama: gereja episcopal yang didirikan sebagai penerus para rasul, rantai penerusan yang tak terputuskan dari tangan para uskup dan pendeta. Karena kuatnya identitas dogmatis dan tata ibadahnya, Ortodoksi relatif lebih damai, meskipun tetap saja ada tekanan dari sekularisasi, contohnya dari Uni Soviet lama, yang mengikis semakin banyak orang untuk keluar. Selain itu, masih ada masalah klasik dari gereja autocephalous (gereja-gereja yang memiliki pemimpin tertinggi sendiri): mereka selalu terancam dari ketergantungan politik dan identifikasi diri pada negara, baik di Yunani, Rusia, Serbia atau negara-negara lain. Karena alasan itulah, reuni dengan Gereja Katolik—tentunya di bawah supremasi Roma— akan sangat berguna bagi gereja-gereja Ortodoks, dan hal itu juga merupakan tujuan yang ingin diraih oleh gereja-gereja di kedua sisi. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh orang-orang di Roma.
Akan tetapi, dari perspektif ekumenis, penghapusan atas pengu- cilan satu sama lain dan pemulihan kembali komuni gereja di Ekaristi— yang secara teoretis telah diutarakan setelah Vatikan II tapi tidak di laksanakan dalam praktiknya—akan menjadi tugas pertama. Mengingat perlunya untuk menghormati batasan-batasan serta kesadaran diri gereja Ortodoks, masa yang dilalui bersama Gereja Katolik akan mampu menghindarkan dari bahaya agama nasional atau agama etnik. Terlebih, pondasi antropologi dari martabat manusia, serta hak dan kewajiban manusia akan lebih bisa dikenali dari keyakinan Kristen bersama, sehingga dunia memiliki etika bersama yang bisa diterima universal.
Di sini juga penting untuk memperingatkan agar tidak muncul harapan palsu: semua kesamaan fitur dogma, tata ibadah, dan hukum gereja yang dimiliki oleh Gereja Katolik Roma serta Gereja Ortodoks tidak bisa menutupi fakta bahwa klaim Roma akan keunggulannya di atas gereja Timur yang telah di nyatakan sejak abad ke-11 merupakan penghalang utama dari penyatuan kembali antara gereja-gereja Barat dan Timur, ditambah lagi dengan adanya doktrin infalibilitas yang dinyatakan pada abad ke-19. Ortodoksi memandang dogma-dogma baru ini sebagai penyimpangan yang nyata oleh Gereja Roma, yang tidak selaras dengan Penjanjian Baru dan tradisi Kristen bersama pada milenium pertama. Selain itu, penunjukan yang semena-mena akan uskup Katolik Roma di daerah teritori Rusia setelah terjadinya perubahan politik, di Siberia bahkan juga di Moscow, yang menunjukkan pembangunan hierarki Roma yang setara dengan hierarki Ortodoks, telah memastikan ketakutan gereja Timur akan imperialisme Roma.
Oleh karenanya, kunjungan Paus di Moscow sejauh ini juga tidak diharapkan (tidak pernah ada undangan resmi dari Putin). Dan kunjungan Paus Benedictus XVI ke Keluarga Konstantinopel juga tidak membuahkan kemajuan yang nyata selain pidato dan isyarat-isyarat ekumenis (umum). Alasan lainnya adalah karena Paus juga tidak memberikan indikasi apa pun bahwa keunggulan yurisdiksi masa abad pertengahan—yang sebenarnya hanya muncul dalam teori Roma— tidak akan bisa digantikan oleh keunggulan kependetaan praktis yang bersih dari segala pretensi.
Tentu saja, semua ini tidak mengecualikan kemungkinan adanya aliansi politik antara Roma pertama dan kedua (Konstantinopel) serta ketiga (Moscow) karena berbagai alasan oportunistis. Akan tetapi ini tidak akan menunjukkan adanya kesatuan ekumenis yang sebenarnya, yang pastinya akan didahului dengan adanya pengakuan dari semua pihak gereja dan persekutuan Ekaristi. Aliansi tersebut bahkan mungkin akan bersifat ‘tidak suci’ jika tujuannya adalah untuk melawan demokrasi, kebebasan beragama dan berkehendak, serta menjunjung tinggi martabat wanita (penolakan atas penahbisan wanita); atau untuk melawan protestanisme atau Dewan Gereja Dunia. Aliansi politik seperti itu hanya akan memperkuat kesan bahwa Gereja Ortodoks hanya mewakili hierarki yang ditunjukkan melalui tata ibadahnya, di mana pada praktiknya proklamasi injil menjadi terabaikan, begitu juga dengan kerja ke-pastur-an di masyarakat dan kritik masyarakat.
Gereja Reformasi sebagai Sebuah Faktor Politik
Kekuatan besar protestanisme terletak pada konfrontasinya pada injil yang selalu diperbaharui, dengan pesan Kristen utamanya yaitu bahwa konsentrasi pada injil merupakan inti dari ‘Protestanisme’, dan hal ini sifatnya mutlak dalam Kristen.
Khusus di abad ke-20, orang-orang telah memiliki pengalaman mengejutkan dengan Dewan Vatikan Kedua, Gereja Katolik, yang sepertinya benar-benar terfosilisasi dalam Kontra-Reformasi dan Anti- modernisasi, telah mengambil langkah mendekati gereja-gereja Kristen lain: ia akhirnya telah mengubah paradigmanya tentang Kristianitas Protestan dari pandangan abad pertengahan menuju Reformasi dalam dimensi-dimensi yang sifatnya fundamental, dan tanpa mengorbankan ke-Katolik-annya mereka telah memikirkan cara untuk fokus pada injil dan sehingga memadukan paradigma Protestan Reformasi (P IV). Serangkaian Pikiran utama Protestan yang telah diakui oleh Gereja Katolik, meski baru secara prinsipil dan belum secara praktis di antaranya: pandangan baru tentang Injil, ibadah populer asli dalam bahasa lokal, penilaian ulang terhadap orang awam, asimilasi gereja ke budaya berbeda dan reformasi ketakwaan populer. Akhirnya, perhatian utama Martin Luther, justifikasi pria dan wanita yang berdosa berdasarkan keyakinan saja, saat ini sama-sama dibenarkan oleh teologi Katolik seperti halnya kebutuhan untuk bekerja dan bertindak atas nama cinta oleh teologi Protestan.
Oportunitas Gereja Reformasi: dari perspektif Roma, Protestanisme dunia tengah berada dalam sebuah proses perubahan yang cepat, yang mana bagi banyak orang mungkin terlihat seperti proses pelapukan yang merusak. Gereja-gereja pengakuan klasik dengan cepat menyusut jumlahnya. Mereka telah berhasil menjaga signifikansinya sebagai kendaraan budaya, akan tetapi mereka semakin kehilangan signifikansinya sebagai rumah agama. Berbagai usaha sering ditempuh untuk mengeluarkan gereja dari krisis ini melalui metode-metode manajemen dan pemasaran modern. Akan tetapi daya utama kehidupan gereja, yang menjadi dasar ada dan tidaknya gereja tidak begitu terlihat lagi. Dan semakin gereja meneruskan perannya hanya sebagai faktor budaya dan masyarakat, semakin mereka masuk jauh ke dalam pencerahan radikal, dan mereka pun larut semakin dalam. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Roma.
Sementara dari perspektif ekumenis, adalah sah-sah saja jika gereja-gereja Protestan mempertajam profil mereka dan menyampaikan inti ajaran mereka dengan lebih jelas. Setiap gereja harus menjaga identitasnya dan menjaganya agar tetap menjadi rumah agama. Ia tidak boleh tunduk pada pokok-pokok pencerahan radikal, atau beradaptasi untuk menyesuaikan diri melalui proses peleburan dengan dunia modern. Akan tetapi, kesalahan terbesarnya bukan karena Protestanisme telah mengalami reformasi signifikan (pernikahan pendeta, moralitas seksual yang lebih terbuka, struktur yang lebih demokratis), akan tetapi pada waktu yang sama ia tidak mengatasi masalah miskinnya substansi dan kurangnya profil dengan cukup tegas.
Disini, Roma juga memiliki harapan palsu: gereja seharusnya tidak merantai dirinya kepada tradisinya sendiri saja; ia tidak boleh menaruh teologi abad pertengahan, teologi Reformasi, dan hukum gereja di atas pengakuan atas Yesus Kristus dan ketuhanan Kristus. Selama berabad- abad Roma telah salah beranggapan tentang pemecahan yang terjadi secara terus-menerus akan diikuti dengan kekosongan spiritual dan akhirnya pembubaran Protestanisme. Perbandingan dari teologi Katolik dan Protestan sendiri menunjukkan seberapa sering teologi Katolik telah tertinggal jauh: semua kemajuan penting dalam eksegesis (tafsir teks) pertama kali dibuat dalam teologi Protestan. Protestanisme jauh dari kata mati bahkan di Eropa maupun di Amerika Utara; ada komunitas yang hidup di kedua area tersebut.
Ancaman dari Mondernitas dan Fundamentalisme
Dalam kerangka paradigma Protestan Reformasi, pergerakan fundamentalis terbentuk di abad ke-19/20 sebagai reaksi atas modernitas (P V). Seorang fundamentalis adalah mereka yang mengakui inspirasi verbal sekaligus ineransi tanpa syarat dari Injil pada masa kini. Dengan kata lain, seseorang yang, pada waktu pra-kritis, memahami Injil secara literal, naif dan tidak kritis bukanlah seorang fundamentalis.
Fundamentalisme mulai terlihat saat muncul dua lapis ancaman terhadap pemahaman tradisional dari keyakinan: di satu sisi ada pandangan dunia tentang sains dan filosofi modern, sebagian dari pemahaman tersebut (khususnya teori evolusi Darwin) bertentangan dengan gambaran dunia yang disajikan oleh Injil. Di lain pihak, kritik Injil modern, yang mulai ada sejak masa Pencerahan dengan metode kritik sejarah, mulai meneliti tentang sejarah asal mula kitab Genesis, kelima kitab Musa secara umum, serta sejarah rumit tentang asal mula tiga Injil sinoptik dan Injil John, yang sangat berbeda dari semuanya. Jadi, fundamentalisme secara otentik merupakan produk dari proses pembelaan diri dan penyerangan terhadap sains, filosofi dan eksegesis modern, yang ditujukan untuk menyelamatkan inspirasi serta inferensi verbal dari Injil dari ancaman modernitas.
Di abad ke-19, teologi Roma juga, seperti biasa dengan keter- tinggalan waktunya, secara luas menerima doktrin inspirasi dan ineransi verbal dari kitab suci (yang telah lama masuk dalam sistem Protestan Ortodoks). Akan tetapi, di waktu yang sama saat inkuisisi Roma yang memperlemah dirinya sendiri dengan proses-proses melawan Galileo dan lainnya, Fundamentalis Amerika juga telah gagal menyebarkan teori ‘creationisme’ mereka (bahwa penciptaan manusia dilakukan secara langsung oleh Tuhan) di sekolah-sekolah negeri.
Baru-baru ini, fundamentalisme juga telah meluas ke agama- agama lain, di antaranya Islam dan Yahudi. Muslim menyebut para eksklusifis ini dengan sebutan literal Islam ‘Islamisme’, sedang Yahudi menyebut mereka secara literal Yahudi sebagai ‘Ultra-Ortodoks’. Akan tetapi jika kita ingin memberi ciri negatif pada keyakinan yang kaku dan literal serta kepatuhan legalistik dari hukum agama, yang seringnya dibarengi dengan keagresifan politik, maka kita akan menemukan bahwa fundamentalisme Muslim dan Yahudi sifatnya sama seperti fundamentalisme Kristen. Tentunya berbagai strategi geopolitik hanya dibuat oleh Kristen (‘Crusade of Christ’—Pejuang Kristus, atau ‘Re- evangelizing Europe’—Peng-Kristenan ulang Eropa) dan Islam (‘Peng- Islaman ulang dunia Arab’). Di sini, terdapat kesamaan pola pemikiran dari garis keras Kristen di AS dan kelompok-kelompok radikal Islam: semua lawan politik merupakan bentuk-bentuk dari kebatilan. Dan penjelmaan perang antara kebaikan melawan kebatilan mampu melegitimasi bahkan penyerangan dan invasi militer. Kita juga tidak boleh melupakan agama-agama yang berasal dari India dan Cina. Hinduisme (melawan Islam, Kristen dan Sikh), atau Confusianisme (melawan Cina non-Han) juga bisa bersikap dengan cara yang eksklusif, otoriter, represif dan fundamental. Dengan kata lain, fundamentalisme merupakan masalah universal, masalah global.
Oportunitas fundamentalisme: apakah yang menjadi sumber dari keefektifan dan dorongan yang sangat besar dari berbagai bentuk fundamentalisme yang berbeda? Ada tiga faktor yang diperkuat dan bekerja sama:
-
Konsistensi: sebuah nilai agama mendasar atau sebuah ide dasar yang tersusun secara konsisten dan terlindungi dengan cara-cara perfeksionis karena kekhawatiran akan munculnya kompromi yang akan melemahkan.
-
Kesederhanaan: cara berpikir, sikap dan sistem yang sederhana dan transparan; perspektif yang tidak sederhana umumnya ditolak.
-
Kejelasan: struktur interpretasi dan doktrin disajikan dengan jelas tanpa ambigu; interpretasi, meskipun halus, ditolak dan dianggap sebagai penyimpangan dari doktrin murni, sehingga dianggap sebagai bid’ah.
Akan tetapi, di sini kita juga tidak boleh memiliki ilusi: apakah doktrin ineransi verbal atau infalibilitas kitab suci menjamin adanya masa depan, apakah kitab suci Yahudi (halakhah), Al-Qur’an atau Perjanjian Baru (atau bahkan dalam kondisi tertentu infalibilitas Paus atau Dewan Reformer) akan menjadi dogma utama dari dogma-dogma lain, sebagai dogma pusat resmi di mana semua keyakinan dan kebenaran akan digantungkan? Seperti halnya Yahudi dan Islam, Kristianitas juga ingin mengomunikasikan orientasi mendasar dari kehidupan manusia di era saat orientasi tersebut tengah melemah. Akan tetapi, bagaimana mungkin fundamentalist Kristen bisa dalam jangka panjang menawarkan interpretasi akan eksistensi sementara dunia merangkul semua aspek kehidupan di waktu yang terus-menerus ditengarai oleh sains, teknologi dan budaya modern jika ia terikat kepada pemahaman literal dari penjabaran tentang penciptaan dan hari akhir, kejatuhan dan hari penebusan?
Pandangan reaksional agama akan dunia ini telah terbukti bersifat merusak saat ia digabungkan dengan kebijakan luar negeri reaksional. Semua orang yang mendukung Amerika versi Lincoln, Kennedy dan Martin Luther King, New Deal, Marshal Plan, Peace Corps, Pergerakan Perdamaian dan Hak-Hak Sipil, dan pemenang penghargaan Nobel Jimmy Carter—semuanya merupakan perwakilan dari Amerika yang demokrasi dan humanistis yang bertahan selama berabad-abad— pasti merasa kecewa dengan peng-orientasi-an ulang dari revolusi kebijakan luar negeri Amerika yang merupakan hasil kerja dari kelompok-kelompok neo-konservatif yang terdiri atas jurnalis dan politisi kekuasaan (yang diaransir oleh kekuatan media). Mereka tidak hanya bergabung dengan lobi Israel yang super kuat (AIPAC), akan tetapi juga dengan fundamentalis Protestan di negara-negara bagian di selatan, yang mana di bawah kepemimpinan para pemikir-pemikir neo- konservatif telah menjadi basis kekuatan penting dari George W. Bush, dengan ribuan massa akar rumputnya. Akan tetapi, sejak pemilihan kongres terakhir dan menimbang Perang Irak yang nihil harapan, dengan korban ribuan dan hutang hingga jutaan dolar, harapan akan perdamaian kini mulai muncul lagi di Amerika.
Berbagai struktur agama tersembunyi telah menjadi titik rujukan darialiansi-aliansibaruini:Yahudisekulerdannon-konservatif(neocon) bisa membuat aliansi dengan fundamentalis Protestan (theocon) yang, menurut Yahudi, seperti George W. Bush, menganggap perang melawan teroris seperti peperangan apokaliptik melawan kebatilan secara umum, dan berdasarkan pemahaman literal akan Injil, menganggap keseluruhan Palestina sebagai ‘tanah suci’ yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada para penganut Yahudi; akan tetapi, bagi mereka negara Israel hanyalah merupakan persangkaan awal dari kembalinya Kristus yang tertulis dalam Perjanjian Baru, dengan perubahan total lanjutan yang dilakukan oleh penganut Yahudi! Pihak Yahudi sendiri sering secara diam-diam menerima ideologi anti-Yahudi selama ia menawarkan keuntungan politis bagi negara Israel dan kebijakan-kebijakannya.
Akan tetapi, pandangan agama fundamentalis ini juga melebur dengan beberapa sikap kebijakan dalam negeri Amerika: melawan aborsi, penelitian stem-cell, dan pernikahan sesama jenis. Sejak terpilihnya Presiden Reagan, pihak ‘sayap kanan religius’—yaitu para penganut Kristen yang aktif secara politik—telah memainkan peran penting di Partai Republik dan membantu Bush Yunior untuk bisa terpilih dua kali. Akan tetapi baru-baru ini, sebuah reaksi yang melawan arus bisa terlihat dalam politik dalam negeri Amerika. Para pemimpin individu dari sayap kanan religius mulai menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi tentang masalah-masalah seperti AIDS, eutanasia (kasus Terri Schiavo) dan ancaman perubahan iklim pada lingkungan.
PANDUAN ETIK BAGI
POLITISI
Pidato oleh
H.E. Kanselir Helmut Schmidt
Di Universitas Turbingen, 8 Mei 2007
PERTAMA-TAMA, saya ingin berterima kasih kepada Hans Kung. Saya sangat gembira menerima undangan ini karena saya telah mengikuti Proyek Etika Global sejak awal tahun 1990-an. Kata ‘Etika Global’ mungkin terdengar terlalu ambisius bagi beberapa orang, akan tetapi tujuannya, tugas yang harus diselesaikan, memang benar-benar, dan memang sebuah keharusan, sangat ambisius. Mungkin saat ini saya bisa menyebutkan sederetan nama kepala negara dan pemerintahan dari kelima benua di dunia yang telah memutuskan untuk mendukung tujuan bersama yang sama persis dengan tujuan ini sejak tahun 1987 seperti tujuan Dewan InterAction (Dewan Inter-Aksi); akan tetapi, saat ini pencapaian kerja kami masih sedikit sekali. Sebaliknya, pencapaian Hans Kung dan koleganya sudah sangat luar biasa.
Saya secara pribadi juga berterima kasih kepada seorang Muslim taat yang pertama kali menginspirasi saya untuk mempertimbangkan ide tentang kesamaan hukum moral pada agama-agama besar. Lebih dari seperempat abad telah berlalu sejak Anwar Al Sadat, saat itu sebagai Presiden Mesir, menjelaskan tentang akar yang sama dari ketiga agama Ibrahim kepada saya, begitu juga banyaknya kemiripan mereka, terutama tentang hukum-hukum moral mereka yang sesuai satu sama lain. Ia mengetahui kesamaan hukum dari ketiga agama tersebut tentang perdamaian, misalnya yang tercantum dalam Kitab Zabur Perjanjian Lama Yahudi, dalam Khotbah Kristen tentang ‘Khotbah di Bukit’, atau dalam surah ke-empat dari Al-Qur’an Muslim. Jika saja orang umum sadar akan titik pertemuan ini, ia yakin; jika saja, paling tidak, para pemimpin politik menyadari adanya kesesuaian etika di antara agama- agama mereka, perdamaian jangka panjang pasti mungkin terjadi. Ia sangat meyakini akan hal ini. Beberapa tahun kemudian, sebagai Presiden Mesir, ia mengambil langkah politik untuk mewujudkan keyakinannya dan mengunjungi ibu kota dan parlemen Negara Israel, yang sebelumnya telah menjadi musuhnya dalam empat perang, untuk menawarkan dan mengusulkan perdamaian.
Di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, saya sudah mengalami duka kehilangan orang tua, saudara kandung dan teman-teman, akan tetapi pembunuhan Sadat oleh penganut agama fanatik adalah kematian yang paling menyedihkan bagi saya, melebihi kematian-kematian lain. Teman saya Sadat terbunuh karena ia menganut hukum perdamaian.
Saya akan segera kembali membahas ide-ide hukum perdamaian, akan tetapi sebelumnya saya akan mengajukan sebuah klausul: sebuah pidato tunggal, khususnya pidato yang panjangnya tidak lebih dari satu jam, tidak akan bisa mencakup semua topik tentang etika politisi. Karena alasan ini, hari ini saya hanya akan fokus pada beberapa hal, yaitu tentang hubungan antara politik dan agama, kemudian pada peran pemikiran dan nurani dalam politik, dan diakhiri dengan perlunya kompromi, dan hilangnya keketatan dan konsistensi sebagai konsekuensi yang akan mengikuti.
I
Sekarang, mari kita kembali kepada hukum perdamaian. Maksim dari perdamaian adalah sebuah unsur penting dari etika moral yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Maksim ini berlaku baik dalam kebijakan dalam negeri suatu negara dan masyarakatnya, dan juga dalam kebijakan luar negerinya. Seiring dengan hal itu, ada hukum-hukum dan maksim- maksim lain. Hal ini termasuk ‘Aturan Emas’ yang diajarkan dan pasti ada di setiap agama di dunia. Immanuel Kant hanya merumuskan ulang hal ini dalam idenya tentang Categorical Imperative; yang sering kita dengar sebagai: “lakukanlah seperti apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu”. Aturan emas ini berlaku pada semua orang. Saya yakin politisi pun tidak memiliki aturan moral dasar lain yang berbeda dari orang kebanyakan.
Akan tetapi, pada level di bawah aturan utama dari moralitas universal, ada banyak adaptasi khusus bagi pekerjaan dan situasi khusus, misalnya dalam Ikrar Hipokratik dokter, atau etika profesional hakim, atau aturan etika khusus yang berlaku bagi pebisnis, bagi banker atau rentenir, bagi pemberi kerja atau tentara saat perang.
Karena saya bukan seorang ahli filosofi atau teologi, saya tidak akan berusaha menyampaikan tentang kompendium atau naskah kuno dari etika politik khusus, dan berkompetisi dengan Plato, Aristoteles atau Konfusius. Selama dua setengah milenium, para penulis besar telah mengumpulkan berbagai jenis unsur atau komponen etika politik, yang kadang-kadang hasilnya bisa sangat kontroversial. Di dunia Eropa modern, hal ini mencakup ide-ide Machiavelli atau Carl Schmitt, hingga ide-ide Hugo Grotius, Max Weber atau Karl Popper. Saya, di lain pihak, akan membatasi bahasan saya pada beberapa pelajaran yang telah saya dapatkan dari pengalaman saya sebagai politisi dan sebagai ahli publisitas politik—sebagian besar di negara saya sendiri, dan sisanya berhubungan dengan negara-negara tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh.
Saat ini, saya ingin membahas pengalaman saya bahwa, meskipun pembicaraan tentang ketuhanan dan Kristianitas sangat jarang ditemukan dalam pembicaraan urusan dalam negeri Jerman, hal itu tidak berlaku dalam diskusi dan negosiasi dengan negara-negara lain dan politisi mereka. Baru-baru ini, saat terjadi referendum di Prancis dan Belanda tentang naskah undang-undang dasar Uni Eropa, banyak orang yang menolak teks undang-undang tersebut hanya karena teks itu kurang memiliki rujukan terhadap Tuhan. Memang, mayoritas politisi memilih untuk tidak melibatkan tuhan dalam teks undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar Jerman sendiri, yang disebut Hukum Dasar, Tuhan muncul dalam pembukaannya “...menyadari akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan...” dan yang kedua dalam redaksional ikrar jabatan di Pasal 56, yang diakhiri dengan: “Bantulah saya, ya Tuhan”. Akan tetapi, segera setelah itu, Hukum Dasar melanjutkan: “Ikrar ini juga bisa diambil tanpa penegasan agama”. Di keduanya, keputusan diserahkan kepada warga negara yang berikrar apakah yang ia maksud Tuhan dari Katolik atau Protestan, atau Tuhan Yahudi atau Muslim.
Dalam kasus Hukum Dasar, adalah juga mayoritas politisi yang merumuskan teks tersebut [ada tahun 1948/49. Di bawah perintah demokrasi, di bawah aturan hukum, politisi dan pemikiran-pemikiran mereka memerankan peran yang menentukan dalam kebijakan konstitusional, alih-alih pengakuan agama tertentu atau kitab suci tertentu.
Baru-baru ini kita mengalami bagaimana, setelah berabad-abad, The Holy See (Dewan Gereja Katolik Roma) akhirnya membalikkan putusan mengenai pemikiran Galileo, yang pada suatu masa pernah dimentahkan oleh politik penguasa. Saat ini, kita bisa melihat setiap hari bagaimana kekuatan-kekuatan agama dan politik di Timur Tengah terlibat dalam peperangan berdarah untuk memperebutkan kekuasaan atas jiwa-jiwa manusia—dan bagaimana pemikiran, rasionalitas yang kita semua miliki, berkali-kali jatuh dan terpinggirkan. Di tahun 2001, saat beberapa fanatik agama mengakhiri hidup mereka sendiri bersama tiga ribu orang lain di New York, yakin bahwa mereka berbuat demikian demi Tuhan mereka; hukuman mati Socrates—yang tanpa tuhan— sudah dua ribu lima ratus tahun di belakang kita. Jelas sekali, konflik abadi antara agama, politik dan pemikiran merupakan unsur kekal dari kondisi manusia.
II
Mungkin saya bisa menambahkan pengalaman pribadi saya di sini. Saya tumbuh pada era Nazi; di awal tahun 1933, saya baru saja berusia empat belas tahun. Selama delapan tahun masa pelayanan militer saya, saya menaruh harapan-harapan saya pada gereja-gereja Kristen selama waktu setelah malapetaka tersebut. Akan tetapi, setelah tahun 1945, saya melihat bagaimana gereja gagal menegakkan ulang moralitas, demokrasi atau negara yang berundang-undang. Bahkan gereja saya sendiri masih berusaha memahami epistel Paul kepada bangsa Romawi:
“Tunduklah pada kekuatan yang lebih tinggi”.
Kemudian, beberapa politisi berpengalaman dari era Weimar memainkan peran penting di awal yang baru tersebut; Adenauer, Schumacher, Heuss dan lain-lain. Akan tetapi, di awal Republik Federal, keadaan tidak sebaik era Weimar yang dulu, alih-alih kesuksesan ekonomi dari Ludwig Erhard dan bantuan Amerika lah yang membawa Jerman menuju kemerdekaan dan demokrasi hingga menjadi negara yang berkonstitusi. Tak ada yang perlu dipermalukan dari kebenaran ini: toh, sejak masa Karl Marx, kita telah tahu bahwa realitas ekonomi mempengaruhi pendirian politik. Kesimpulan ini mungkin hanya mencakup semua kebenaran, akan tetapi faktanya adalah bahwa semua demokrasi berada dalam bahaya jika otoritas pemerintahannya tidak bisa menjaga industri dan tenaga kerjanya tetap terkontrol dan teratur.
Hasilnya, saya tetap kecewa pada bentuk-bentuk pengaruh gereja, tidak hanya secara moral, tapi juga secara ekonomi dan politik. Selama seperempat abad saat saya menjabat sebagai Konselor, saya telah mempelajari banyak hal baru dan saya telah banyak membaca. Dalam proses ini, saya telah sedikit belajar tentang agama-agama lain serta filosofi-filosofi yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Pemahaman ini telah memperluas toleransi beragama saya; dan di waktu yang sama, ia telah menjauhkan saya dari Kristianitas. Akan tetapi, saya masih menganggap diri saya Kristen dan tetap pergi ke gereja, karena hal itu bisa menjadi penyeimbang dari penurunan moral dan menawarkan adanya dukungan dari banyak orang.
III
Hingga saat ini, hal yang terus mengganggu saya tentang rujukan kepada Tuhan umat Kristen—baik di antara para warga gereja maupun di antara sesama politisi—adalah kecenderungan untuk mengeluarkan kelompok lain yang tidak selaras dengan Kristianitas—dan hal ini juga bisa ditemukan dalam pengakuan agama lain: “Kalian salah dan saya lah yang telah mendapat pencerahan; keyakinan dan tujuan saya adalah milik Ilahi”. Telah lama jelas bagi saya bahwa perbedaan agama dan ideologi kita tidak boleh menghentikan kita dari terus bekerja demi kebaikan semua orang; karena, nilai-nilai moral kita sebenarnya sangat mirip satu sama lain. Perdamaian di antara kita sebenarnya sangatlah mungkin terjadi, akan tetapi ia harus selalu diciptakan ulang dan‘dibangun’, seperti yang dituturkan oleh Kant.
Adalah tidak sesuai dengan tujuan perdamaian jika penganut dan pendeta suatu agama mencoba mengubah keyakinan pemeluk agama lain dan mendakwahkan agamanya kepada mereka. Untuk alasan inilah, sikap saya sangat skeptis terhadap ide dibalik pengiriman misionaris untuk menyebarkan ajaran agama tertentu. Pengetahuan saya tentang sejarah memainkan peran penting dalam hal ini—saya merujuk pada fakta bahwa, selama berabad-abad, baik Kristen dan Islam disebarkan melalui pedang, dengan peperangan dan penundukan, dan bukan melalui komitmen, keyakinan, dan pemahaman. Para politisi Abad Pertengahan; yaitu para bangsawan dan raja-raja, khalifah dan paus, membenarkan pemikiran-pemikiran misionaris agama dan menggunakannya sebagai alat untuk memperluas kekuasaan mereka—dan ribuan pemeluk agama secara sukarela membiarkan dirinya digunakan untuk tujuan ini.
Dalam pandangan saya, misalnya, Perang Salib atas nama Kristus, di mana para tentara memegang Injil di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, benar-benar merupakan perang penaklukan. Di era modern ini, Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Prancis serta Jerman sendiri menggunakan kekerasan untuk mengambil alih sebagian besar wilayah Amerika, Afrika dan Asia. Benua-benua asing ini mungkin telah dijajah berdasarkan keyakinan atas keunggulan moral dan agama, akan tetapi pendirian imperium kolonial ini tidak ada hubungannya dengan Kristianitas. Alih-alih, ini semua tentang kekuasaan dan kepentingan yang sifatnya egosentris. Atau, ambil contoh Reconquista (penaklukan) Semenanjung Iberia; ia bukan hanya mengenai kemenangan Kristianitas, akan tetapi lebih tentang kekuasaan monarki Katolik, Ferdinand dan Isabela. Saat Hindu dan Islam saling berperang di tanah India saat ini, atau saat Muslim Sunni dan Syiah berperang di Timur Tengah, lagi dan lagi inti utama dari masalahnya adalah kekuasaan dan kontrol—agama dan pendeta hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa.
Dewasa ini, saya sangat sedih karena di awal abad ke-21 sebuah bahaya besar ‘bentrokan kebudayaan’ dunia telah berkembang, yang termotivasi atau berkedok alasan-alasan agama. Di beberapa bagian di dunia modern, motif kekuasaan di bawah kedok agama, yang bercampur dengan amarah karena kemiskinan dan kedengkian atas kesuksesan pihak lain. Motif-motif misionaris agama bercampur dengan motif kekuasaan yang berlebih. Dalam konteks ini, sulit bagi suara-suara pemikiran yang logis, seimbang dan menenangkan untuk terdengar. Sekumpulan orang yang bersemangat dan ekstatik tidak akan bisa mendengar seruan pemikiran yang logis. Hal yang sama saat ini juga berlaku di tempat-tempat di mana ideologi dan ajaran Barat mengenai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, yang sebenarnya sangat terhormat, dipaksakan dengan kekuatan militer dan gairah religius kepada budaya-budaya lain yang sebelumnya telah mengembangkan sikap yang jauh berbeda.
IV
Saya sendiri telah mengambil kesimpulan yang jelas dari berbagai pengalaman ini: jangan percaya pada politisi, kepala negara atau pemerintahan, yang mengubah agama mereka menjadi alat penaklukan dan kekuasaan. Jauhilah politisi yang mencampur adukkan agama, yang berorientasi membuat dunia baru, dengan politik mereka di dunia ini.
Peringatan ini ditujukan baik bagi politik dalam negeri maupun luar negeri. Juga berlaku sama bagi warga negara sebuah bangsa maupun para politisinya. Kita harus mendesak para politisi agar menghormati dan menoleransi para pemeluk agama lain. Pemimpin politik yang tidak bisa melakukan ini harus dianggap sebagai risiko bagi perdamaian— baik perdamaian dalam negara kita sendiri atau perdamaian dengan negara lain.
Adalah sebuah tragedi saat, di semua sisi, para rabbi, pendeta dan pastur, serta mullah dan ayatollah telah, sangat dengan dalam menyimpan semua pengetahuan tentang agama lain dari kita semua. Alih-alih, mereka telah mengajarkan kepada kita dengan cara yang berbeda-beda untuk melihat agama lain secara sepihak dan bahkan untuk memandang rendah agama-agama tersebut. Akan tetapi, siapa pun yang mengharapkan adanya perdamaian di antara agama-agama harus mengkhutbahkan tentang toleransi dan rasa hormat terhadap agama lain. Rasa hormat terhadap agama lain membutuhkan setidaknya sedikit pengetahuan tentang agama tersebut. Telah lama saya meyakini bahwa ketiga agama Ibrahim serta Hinduisme, Budhisme, dan Shintoisme juga mengharapkan adanya rasa saling menghormati dan toleransi.
Karena keyakinan saya ini, saya sangat menyambut Deklarasi Chicago “Menuju Etika Global” yang diselenggarakan oleh Parlemen Agama-Agama Dunia. Menurut saya konferensi ini bukan hanya diharapkan, tapi diperlukan. Berdasarkan sikap fundamental yang sama, sepuluh tahun yang lalu di hari ini, Dewan InterAction yang terdiri atas para mantan kepala negara dan pemerintahan mengirimkan sebuah naskah yang berjudul “Deklarasi Universal tentang Tanggung Jawab Manusia” kepada Sekretaris Jenderal PBB. Naskah ini telah kami susun atas inisiatif Takeo Fukuda dari Jepang. Naskah tersebut, yang ditulis dengan bantuan dari semua perwakilan agama-agama besar, memuat prinsip-prinsip fundamental dari kemanusiaan. Pada titik ini, saya ingin berterima kasih kepada Hans Kung atas bantuannya. Di waktu yang sama, saya merasa bersyukur saat mengingat kontribusi besar yang dibuat oleh Franz Kardinal Konig dari Vienna.
V
Akan tetapi, saya kini juga telah memahami bahwa, dua ribu lima ratus tahun yang lalu, beberapa guru besar kemanusiaan seperti Socrates, Aristoteles, Konfusius dan Mencius, tidak memerlukan agama, meski mereka mereka menyuarakan hal yang sama, karena mereka memang diharapkan untuk melakukannya, meskipun lebih sebagai pekerjaan. Semua yang kita ketahui tentang mereka memberi tahu kita bahwa Socrates mendasarkan filosofinya, serta Konfusius mendasarkan etikanya, hanya kepada penggunaan pemikiran; semua ajaran mereka tidak ada yang berbasis agama. Akan tetapi, keduanya telah berhasil memimpin jutaan manusia, bahkan hingga saat ini. Tanpa Socrates, Plato tidak akan ada—mungkin bahkan tidak akan ada Immanuel Kant maupun Karl Popper. Tanpa Konfusius dan Confusianisme, sulit untuk membayangkan budaya CIna dan ‘Kerajaan Sutera’, yang kurun waktu dan vitalitasnya sangat unik dalam sejarah dunia, ada ada.
Di sini, ada satu pelajaran yang sangat penting bagi saya: jelas sekali, adalah mungkin untuk mendapatkan wawasan, pencapaian ilmiah, serta ajaran-ajaran etika dan politik yang hebat, meskipun penggagasnya tidak menganggap dirinya terikat kepada satu Tuhan, kepada seorang nabi, kepada sebuah Kitab Suci, atau kepada agama tertentu, tapi hanya terikat kepada pemikiran-pemikirannya sendiri. Hal ini juga berlaku kepada berbagai pencapaian sosial ekonomi serta politik. Akan tetapi, Pencerahan Amerika dan Eropa ini harus dibayar dengan perjuangan dan peperangan berabad-abad sebelum pengalaman ini bisa disadari sebagai terobosan di belahan dunia kita ini. Di sini, kata ‘terobosan’digunakan seperti dalam sains, teknologi dan industri.
Akan tetapi, dalam hubungannya dengan politik, kata ‘terobosan’
ternyata hanya berlaku pada Pencerahan yang jangkauannya terbatas. Apakah itu berupa Wilhelm II yang menganggap dirinya sebagai seorang kaisar ‘atas keagungan Tuhan’, atau presiden Amerika yang menggunakan ‘Tuhan’, atau politisi yang mencampur adukkan nilai- nilai Kristianitas dengan politik mereka: mereka menganggap diri mereka terikat kepada agama Kristen. Beberapa bahkan secara jelas merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab religius Kristen; sementara ada juga yang melihat tanggung jawab ini secara samar— seperti yang mungkin dilakukan oleh kebanyakan orang Jerman saat ini. Banyak orang Jerman yang saat ini telah memutuskan diri dari Kristianitas, banyak yang telah meninggalkan gereja mereka; beberapa bahkan ada yang memisahkan diri dari Tuhan—akan tetapi mereka tetap menjadi orang serta tetangga yang baik.
VI
Dewasa ini, mayoritas penduduk Jerman memiliki kesamaan keyakinan politik yang fundamental yang mampu menyatukan mereka. Lebih dari itu, mereka terikat dalam nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan prinsip- prinsip demokrasi yang tak bisa dipisahkan. Komitmen dalam diri ini telah terbukti tidak terpengaruh keyakinan atau tidak adanya keyakinan pada diri mereka, dan juga terpisah dari kenyataan bahwa keduanya tidak termuat dalam denominasi Kristianitas.
Tidak hanya Kristen, agama-agama lain di dunia serta kitab-kitab sucinya juga telah memaksakan berbagai hukum dan kewajiban kepada para penganutnya, sementara hak-hak individu jarang dibahas dalam kitab-kitab suci. Selain itu, di 20 pasal pertamanya, hampir semua pasal di Hukum Dasar kita membahas tentang hak-hak konstitusi dari warga negara secara individu, sementara tugas dan tanggung jawab mereka sama sekali tidak disebutkan. Daftar hak-hak asasi manusia kita merupakan reaksi yang sehat dari penindasan ekstrem dari kebebasan individu yang diterapkan di era Nazi. Ia tidak dibangun di atas ajaran- ajaran Kristianitas atau agama lain, tapi seluruhnya hanya berdasarkan nilai-nilai yang secara tegas telah diutarakan dalam undang-undang dasar kita: “martabat manusia yang tak bisa dilanggar”.
Dengan nafas yang sama, di Pasal 1, dewan legislatif, eksekutif dan yudisial juga terikat oleh hak-hak dasar sebagai hukum yang bisa diterapkan secara langsung; hal ini juga berarti bahwa semua politisi juga terikat, apakah mereka pembuat hukum, otoritas pemerintah atau administrator; apakah mereka di pemerintahan pusat, di negara bagian atau di kota kabupaten. Di waktu yang sama, para politisi tersebut memiliki jangkauan yang sama luasnya untuk mengambil tindakan, karena Hukum Dasar memungkinkan munculnya politik yang bagus dan sukses maupun politik yang kurang bagus dan kurang sukses. Untuk alasan inilah, kita tidak hanya membutuhkan ketaatan para pembuat hukum dan pihak penguasa kepada undang-undang dasar; bukan hanya karena, alasan kedua, adanya aturan yang mengatakan hal tersebut di Pengadilan Konstitusi, akan tetapi juga karena, alasan ketiga dan terpenting, aturan politik oleh para pemilih serta opini publik.
Sudah barang tentu, para politisi takut akan teror; mereka juga bisa membuat kesalahan. Mereka juga manusia yang memiliki kelemahan manusiawi yang sama seperti warga negara lain, kelemahan yang sama seperti yang diutarakan oleh opini publik. Dari waktu ke waktu, politisi selalu dipaksa untuk membuat keputusan spontan; akan tetapi, seringnya mereka memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mencari berbagai saran dari sumber-sumber berbeda, untuk mempertimbangkan berbagai pilihan berbeda serta berbagai konsekuensi yang bisa diperkirakan sebelum akhirnya membuat keputusan. Semakin politisi membiarkan diri mereka disetir oleh teori atau ideologi tertentu, atau oleh kepentingan partainya, semakin sedikit ia mempertimbangkan semua faktor yang seharusnya dipertimbang- kan serta berbagai konsekuensi dari keputusannya pada kasus-kasus individual; sehingga semakin besar pula kesempatan untuk adanya kesalahan dan kegagalan. Di semua kasus, politisi inilah yang harus bertanggung jawab atas semua konsekuensinya—dan di situlah tang- gung jawabnya mulai terasa seperti beban yang berat. Dalam banyak kasus, politisi kadang tidak mendapatkan bantuan dalam pembuatan keputusan baik dari konstitusi, dari agama mereka, atau dari teori dan filosofi manapun, dan mereka harus mengandalkan pemikiran dan pertimbangan mereka saja.
Karena alasan inilah Max Weber agak terlalu luas saat ia menyam- paikan pidatonya di tahun 1919 yang masih bisa kita baca hingga saat ini tentang ‘politik sebagai profesi’ dari ‘rasa keadilan’ seorang politisi. Dia juga menambahkan bahwa seorang politisi harus bisa “memberikan sebuah hasil bagi setiap tindakannya”. Selain itu, saya yakin bahwa hasil yang diberikan bukan hanya hasil secara umum, tapi juga efek samping yang tidak diinginkan atau yang bisa ditoleransi harus di justifikasi; serta cara dan alatnya harus bisa dipertanggung-jawabkan secara etis. “Rasa keadilan” harus, sekali lagi, bisa melengkapi berbagai keputusan spontan yang harus diambil dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, jika masih ada waktu untuk mempertimbangkan berbagai faktor, setiap keputusan harus didahului dengan analisa dan kajian yang seksama. Maksim ini tidak hanya berlaku pada berbagai keputusan ekstrem, kasus dramatis, akan tetapi juga kepada legislasi normal harian misalnya tentang pajak atau kebijakan buruh; juga berlaku sama bagi berbagai keputusan tentang pembangunan pembangkit listrik baru atau jalan raya baru. Ia berlaku tanpa ada batasan.
Dengan kata lain, politisi tidak bisa membenarkan tindakan mereka, dan konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut, hanya dengan kata hati mereka kecuali jika mereka telah menerapkan pemi- kiran-pemikiran logis. Niat dan keyakinan yang baik saja tidak akan bisa meringankan beban tanggung jawab mereka. Untuk alasan inilah saya selalu menganggap kata-kata Max Weber sebagai keharusan etika tanggung jawab, dan bukan sebagai etika untuk membenarkan tujuan akhir, sebagai acuan etika yang paling valid.
Akan tetapi, di waktu yang sama, kita tahu bahwa banyak orang yang memasuki dunia politik karena terdorong oleh keyakinan mereka, dan bukan oleh pemikiran logis. Sehingga, kita harus melihat banyak keputusan, baik tentang berbagai urusan domestik maupun luar negeri, dilahirkan hanya dari keyakinan beberapa orang, dan bukan dari berbagai pertimbangan rasional. Dan semoga kita tidak memiliki ilusi tentang fakta bahwa sebagian besar pemilih hanya mendasarkan pilihan politik mereka berdasarkan keyakinan—atau pada dorongan suasana hati saja.
Meski demikian, saya telah mengutarakan kepentingan yang fundamental dari dua unsur pembuatan keputusan politis—pemikiran logis dan suara hati—baik dalam pidato maupun secara tertulis selama bertahun-tahun.
VII
Bagaimanapun, saya harus menambahkan bahwa, meskipun kesim- pulan ini terlihat atau terdengar sederhana dan tanpa ambigu, ia tidak sesederhana itu pada kenyataan dinamika demokratis. Dalam pemerintahan sistem demokratis, adalah tidak diperbolehkan jika hanya satu orang yang membuat keputusan politis. Dalam sebagian besar kasus yang pernah ada, yang membuat keputusan bukanlah satu orang individu, akan tetapi mayoritas orang. Hal ini misalnya berlaku bagi semua legislasi, tanpa terkecuali.
Demi mendapatkan suara legislasi mayoritas di parlemen, ratusan orang harus menyetujui sebuah teks bersama. Sebuah isu yang sejatinya tidak terlalu penting bisa, di waktu yang sama, menjadi rumit dan sulit untuk dicari solusinya. Dalam kasus seperti ini, sangat mudah untuk mengandalkan seorang ahli atau pemimpin yang sudah dikenal di partai parlemen tertentu, akan tetapi ada banyak kasus di mana beberapa anggota parlemen memulai dengan opini yang sangat berbeda dan sangat berdasar tentang satu atau beberapa hal. Pemikiran mereka harus di akomodasi agar mereka bisa setuju.
Dengan kata lain, pembuatan keputusan dan legislasi oleh mayoritas parlemen berarti bahwa semua individu harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan kompromi! Tanpa adanya kompromi, konsensus mayoritas tidak akan bisa dibentuk. Orang- orang yang, pada prinsipnya, tidak bisa atau tidak mau berkompromi adalah tidak berguna bagi legislasi demokratis. Harus diakui, kompromi memang seringnya berarti hilangnya keketatan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi seorang anggota parlemen yang demokratis harus mau menerima kehilangan seperti ini.
VIII
Kompromi hampir selalu diperlukan dalam pembuatan kebijakan luar negeri agar perdamaian antarnegara tetap terjaga. Sacro egoism suatu negara, seperti yang saat ini diterapkan oleh pemerintah AS, tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama.
Memang benar bahwa dalam jangka waktu ribuan tahun—dari era Alexander hingga Caesar, dari era Genghis Khan, Pizzaro atau Napoleon, hingga era Hitler dan Stalin—idealisme perdamaian sangat jarang memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan luar negeri. Ia juga sama jarangnya berperan dalam etika pemerintahan teoretis atau dalam integrasi filosofi dalam politik. Sebaliknya, selama ribuan tahun, bahkan dari Machiavelli hingga Clausewitz, perang selalu diabaikan sebagai sebuah unsur politik.
Baru di era Pencerahan Eropa, sejumlah kecil penulis—misalnya Dutchman, Hugo Grotius, atau penulis Jerman Immanuel Kant— mulai meninggikan perdamaian menjadi sebuah idealisme politik yang diinginkan. Meski begitu, bagi sebagian besar negara-negara Eropa di sepanjang abad ke-19, perang tetap menjadi perpanjangan tangan dari politik. Orang-orang telah lama memandang perang sebagai kejahatan utama dari kemanusiaan, yang harus dihindari; tapi baru setelah keterpurukan hebat pasca dua perang dunialah pandangan ini bisa mencapai para politisi dunia Barat dan Timur. Hal ini bisa dilihat dari adanya usaha untuk membuat Perhimpunan Negara-Negara, kemudian pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tetap berdiri hingga saat ini; ini juga terlihat pada perjanjian pembatasan senjata yang ditujukan untuk penciptaan keseimbangan antara AS dan Uni Soviet, dan juga dari pendirian integrasi Eropa sejak tahun 1950-an dan dari Ostpolitik Jerman di awal 1970-an.
Secara tidak sengaja, Ostpolitik Bonn ke Moscow, Warsawa dan Praha menjadi contoh yang menarik sebagai unsur penting dari kebijakan-kebijakan perdamaian: seorang negarawan yang ingin melakukan tindakan atas nama perdamaian harus berbicara dengan negarawan di sisi lain (yang merupakan musuh potensial!) dan harus mendengarkannya! Berbicara, mendengar dan, jika memungkinkan, melakukan kompromi. Contoh lain yaitu pada Langkah Final dari Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (Deklarasi Helsinki) di tahun 1975, yang merupakan kompromi atas nama perdamaian. Uni Soviet mendapatkan tanda tangan para negarawan Barat di bawah deklarasi inviolabilitas dari Perbatasan Eropa Timur dan negara-negara Barat mendapatkan tanda tangan kepala negara Komunis tersebut di bawah poin-poin hak asasi manusia (yang nantinya menjadi seterkenal Basket Three of the Accords). Runtuhnya Uni Soviet pada satu setengah dekade ke depannya bukanlah karena dorongan militer dari luar—puji Tuhan!—akan tetapi karena ledakan sistem dalam negeri yang telah jauh melampaui kekuatannya sendiri.
Contoh negatif yang berkebalikan dari idealisme perdamaian adalah berbagai perang dan tindakan kekerasan yang bertahan selama berabad-abad antara Negara Israel dengan tetangga Palestina dan negara-negara Arab. Jika kedua pihak tidak ada yang mau berbicara dan melakukan kompromi, perdamaian hanya akan menjadi harapan ilusif.
Sejak tahun 1945, hukum internasional, berbasis Piagam PBB, telah melarang segala bentuk intervensi eksternal untuk segala urusan dalam negeri suatu negara melalui kekerasan, dan hanya Dewan Keamanan yang berhak memutuskan pengecualian atas aturan dasar ini. Misalnya, intervensi militer di Irak, apalagi yang didasarkan pada kepalsuan, jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip non-intervensi, sebuah pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB. Para politisi dari banyak negara sama-sama bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini. Sama halnya, para politisi dari banyak negara, (termasuk Jerman) sama-sama bertanggung jawab atas intervensi yang bertolak belakang dengan hukum internasional yang berdasarkan atas asas kemanusiaan. Misalnya, selama lebih dari satu dekade, konflik kepentingan yang sengit di negara-negara Balkan telah ditutupi dengan mantel kemanusiaan oleh Barat (termasuk pengeboman di Belgrade).
IX
Meski demikian, saya akan meninggalkan isu penyelewengan terhadap kebijakan luar negeri ini dan kembali kepada topik kompromi parlemen. Media massa, yang, dalam masyarakat terbuka ini, sangat mampu membentuk opini publik, kadang menganggap kompromi politik sebagai kompromi ‘perdagangan kuda’ atau kompromi ‘malas’, dan kadang mereka dibuat marah oleh kekurangdisiplinan partai yang dianggap tidak bermoral. Meskipun, di lain pihak, adalah hal yang bagus dan berguna jika media terus mengawal dengan kritis proses pembentukan opini ini, akan tetapi harus dipahami bahwa teorema tentang keharusan demokratis ini tetap merupakan suatu kebenaran. Pada kenyataannya, sebuah dewan legislatif yang mana anggota-anggotanya kaku tanpa sedikit pun melenturkan opini individual mereka hanya akan membawa negara menuju kekacauan. Semua menteri dalam pemerintahan dan semua anggota parlemen pasti mengetahui hal ini. Semua politisi tahu bahwa mereka harus melakukan kompromi. Tanpa adanya prinsip- prinsip kompromi, tidak mungkin akan ada prinsip-prinsip demokrasi.
Akan tetapi, pada kenyataannya, memang ada yang dinamakan dengan kompromi yang buruk—misalnya kompromi yang merugikan pihak ketiga atau yang merugikan generasi selanjutnya. Ada juga kompromi yang setengah-setengah, yaitu kompromi yang tidak sepenuh- nya mengatasi masalah yang ada, tapi hanya membuatnya seolah telah terselesaikan. Dengan begitu, nilai-nilai baik dari sebuah kompromi menjadi terancam rusak karena adanya godaan oportunisme. Godaan untuk melakukan kompromi oportunistik dengan opini publik, atau dengan berbagai unsur opini publik, muncul hampir setiap hari! Untuk alasan ini, politisi yang mau untuk berkompromi harus bergantung pada panggilan hati mereka secara personal.
Ada kompromi yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang politisi, karena kompromi tersebut tidak sesuai dengan panggilan jiwa mereka. Dalam kasus seperti ini, satu-satunya hal yang menghalanginya hanyalah ketidaksepakatan publik; dalam beberapa kasus, hal ini bisa berujung pada pengunduran diri atau hilangnya kursi di parlemen. Keputusan yang bertentangan dengan panggilan hati seseorang mampu menggerogoti moral dan kehormatan orang tersebut—serta mampu menghilangkan kepercayaan terhadap integritas orang tersebut.
Akan tetapi ada juga yang disebut dengan kesalahan kompromi. Pemikiran logis seseorang kadang bisa salah, begitu juga panggilan hati. Dalam kasus seperti ini, kritik moral tidaklah dibenarkan, sementara kerusakan yang besar mungkin saja dilakukan. Jika, dalam kasus seperti ini, politisi tersebut di kemudian hari mengenali kesalahannya, ia akan diharuskan pada pilihan untuk mengakui kesalahannya tersebut dan mengatakannya dengan jujur dan terbuka atau tidak. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan politisi umumnya mengambil tindakan yang sangat manusiawi, sama seperti kita semua yang ada di ruangan ini: sangat sulit bagi kita untuk mengakui kesalahan akan suara hati kita sendiri dan mengatakan kejujuran tersebut di depan publik.
X
Pembahasan tentang kebenaran kadang bisa bersifat kontras dengan semangat yang disebut Max Weber sebagai salah satu sifat unggul dari seorang politisi. Pembahasan tentang kebenaran kadang juga bisa kontras dengan syarat kemampuan retorika yang telah dianggap sebagai salah satu seni yang paling penting sejak dua ribu lima ratus tahun yang lalu di masyarakat Demokratis Athena—dan yang telah menjadi jauh lebih penting saat ini di masyarakat yang telah mengenal televisi. Politisi yang ingin dipilih harus mampu menyajikan pada warganya apa yang menjadi keinginan mereka, serta manifestasi keinginan tersebut. Dalam melakukan hal itu, mereka terancam untuk mengatakan lebih dari yang mereka mampu penuhi, terutama saat mereka mencoba menarik hati para audiens televisi. Semua orang yang kampanye rentan terhadap godaan untuk berbicara besar. Kompetisi untuk membangun prestise, dan lebih dari itu untuk menarik hati para pemirsa televisi, telah mempertinggi godaan tersebut dibandingkan dengan saat masyarakat hanya membaca koran di zaman dulu.
Demokrasi massa modern yang kita miliki saat ini, tidak seperti yang dikatakan oleh Winston Churchill dulu, merupakan bentuk pemerin- tahan yang jauh lebih baik—dibandingkan dengan semua bentuk lain yang telah kita coba dari waktu ke waktu, meski ia bukan yang paling ideal. Ia masih sering dilanda godaan, kesalahan, maupun kekurangan. Yang sudah pasti adalah fakta positif bahwa masyarakat pemilih bisa mengganti pemerintahan tanpa harus didahului dengan kekerasan atau pertumpahan darah, dan untuk alasan itulah para politisi terpilih dan parlemen mayoritas di balik mereka harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka di depan para pemilihnya.
XI
Seperti semangat dan rasa keadilan, Max Weber meyakini sifat ketiga dari seorang politisi adalah rasa tanggung jawab. Pertanyaannya: tang- gung jawab kepada siapa? Bagi saya, warga pemilih bukanlah otoritas terakhir yang harus diberi tanggung jawab oleh seorang politisi, pemilih seringnya hanya membuat keputusan yang sangat umum dan bersifat mengikuti trend, dan mereka sering membuat keputusan berdasarkan perasaan dan dorongan hati. Meski begitu, keputusan mayoritaslah harus dipatuhi oleh para politisi.
Bagi saya, otoritas final tetap berupa panggilan hati, meski saya menyadari ada banyak opini teologis dan filosofis tentang panggilan hati ini. Istilah ini bahkan telah digunakan sejak era Yunani dan Romawi. Kemudian, Paul dan para ahli teologi lain menggunakannya untuk merujuk kepada kesadaran kita tentang Ketuhanan dan perintah- perintah Tuhan yang disampaikan oleh para pendeta, dan di waktu yang sama, kesadaran kita bahwa pelanggaran terhadap perintah-perintah tersebut dianggap sebagai dosa. Beberapa penganut Kristen mengatakan bahwa ‘suara Tuhan ada di dalam diri kita”. Dalam tulisan teman saya Richard Schroder saya membaca bahwa pemahaman kita tentang panggilan hati berasal dari pemikiran tentang Injil yang bersentuhan langsung dengan dunia: tentang Helenisme. Di lain pihak, di sepanjang hidupnya, Immanuel Kant tidak pernah memikirkan tentang nilai- nilai mendasar dari panggilan hatinya dengan dasar agama. Kant mendeskripsikan panggilan hati sebagai “kesadaran akan rasa keadilan pada diri manusia”.
Apakah orang meyakini panggilan hati berasal dari pemikiran atau berasal dari Tuhan—apa pun itu, tidak ada yang meragukan bahwa manusia memiliki panggilan hati. Baik orang itu Kristen, Muslim, Ya- hudi, agnostik atau pemikir bebas, manusia dewasa pasti memiliki panggilan hati. Saya akan menambahkan dengan sedikit diam-diam: kita semua harus hidup ‘dengan panggilan hati untuk merasa bersalah”. Tentunya, kelemahan manusiawi ini juga dimiliki oleh seorang politisi.
XII
Sejauh ini, saya telah mencoba mendeskripsikan tentang berbagai wa- wasan yang saya dapatkan dari pengalaman selama tiga dekade menjadi seorang politisi profesional. Tentunya, semua yang saya sampaikan hanya merupakan inti yang sangat terbatas dari sebuah realitas yang memiliki berbagai faset. Satu wawasan ganda terakhir yang sangat penting bagi saya: pertama, masyarakat terbuka dan demokratis kita masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, dan semua politisi juga masih memiliki kelemahan yang sangat manusiawi. Adalah kesalahan besar jika kita berpikir bahwa kehidupan demokrasi kita saat ini sudah ideal. Akan tetapi, yang kedua, kita bangsa Jerman, karena sejarah kita yang katastrofik, kita harus tetap berpegang teguh kepada demokrasi sekuat tenaga kita, dengan terus meremajakannya dan menjaganya dengan berani di depan musuh-musuh demokrasi. Hanya jika kita meyakini semua inilah lagu kebangsaan nasional negara kita, yang memiliki lirik ‘Kesatuan, Keadilan dan Kebebasan’, bisa dibenarkan.
ANALEK KONG HUAN
Makalah dipresentasikan oleh
Dr. Tu Weiming
Universitas Harvard dan Universitas Peking
ANALEK merupakan, saya yakin, distilasi dari apa yang pastinya merupakan serangkaian persimpangan dari ilmu Konfusius (551-479 AD) yang kaya, bervariasi, spontan, tepat waktu, dinamis, patut dikenang dan sangat menggugah pikiran, dengan para murid dan penganutnya selama beberapa dekade. Mungkin membutuhkan dua generasi pengikut Konfusius yang paling dekat dan pintar untuk mengumpulkan ‘kitab’ Analek. Dan sepertinya kitab tersebut memang tidak direncanakan untuk menjadi produk yang benar-benar selesai. Alih-alih, mereka mungkin memang sengaja membuatnya terbuka sehingga kontribusi baru masih bisa diterima, tapi sangat jelas bahwa mereka sangat berhati-hati dan bijaksana dalam memilih setiap entri yang masuk. Alasan dari strategi ini tidaklah sulit untuk dibayangkan. Dengan berasumsi bahwa tujuan dari kompilasi tersebut adalah untuk mengenang guru mereka, seorang manusia yang paradigmatis, yang mereka rindukan, puja, hormati dan cintai. Ada beberapa kemungkinan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mereka bisa menceritakan berbagai aktivitas penting dari guru mereka, menulis bersama sebuah biografi penghargaan, atau merekam secara sistematis ide-ide inti dari ajarannya. Alih-alih, mereka memilih gaya penyampaian yang sangat personal, merekam secara otentik bagaimana ia berbicara, bertindak, berpikir, dan yang paling jelas, bagaimana ia merespons berbagai pertanyaan khusus. Dan langkah ini telah berhasil dengan sangat gemilang.
Sebagai sebuah kitab klasik, Analek bersifat terbuka. Ia terbuka terhadap berbagai tambahan baru, kosakata berbeda, komentar yang tak seragam, serta interpretasi baru. Teks nya secara alami memang bersifat terbuka pada berbagai jaringan kontributor yang semakin membesar. Ia menjadi semacam ruang publik yang luas, yang memiliki banyak ruang untuk mengakomodasi berbagai wawasan dan pemahaman yang bisa diatributkan kepada Sang Guru. Ada setidaknya tiga versi Analek yang terekam dalam bibliografi sejarah. Karena banyaknya jumlah pernyataan yang dimulai dengan ‘Guru mengatakan” yang tersebar di banyak teks Pra-Qin (abad ketiga AD), banyak ilmuwan kritis yang mengutarakan keraguan atas reliabilitas dari pernyataan-pernyataan tersebut. Mereka yang berhati-hati, di bawah pengaruh pemikiran yang ‘meragukan kekunoan’, bahkan menyatakan pernyataan-pernyataan dalam Analek patut dicurigai. Kesan bahwa semua pernyataan Sang Guru yang terekam bersifat derivatif dan sehingga kita tidak bisa yakin bahwa mereka benar-benar mencerminkan pemikiran Sang Guru sangat kental di antara para Sinologis. Karena Konfusius tidak berkutik, setidaknya di lingkaran para ilmuwan, pencarian akan Konfusius yang asli telah menjadi obsesi utama para Sinologis.
Situasi ini berubah secara dramatis dengan penemuan Guodian sejak tahun 1992. Untuk pertama kalinya, para arkeolog dan ilmuwan teks dihadapkan pada lajur-lajur bambu penuh teks yang dibuat sejak abad keempat AD, yang berisi sumber-sumber utama dari para murid generasi pertama Konfusius dan, yang paling mengejutkan, rekaman dari komentar-komentar Sang Guru pada kitab-kitab klasik tersebut. Reliabilitas dari kitab Analek menjadi jauh terangkat. Beberapa atribusi lain kepada Konfusius, misalnya yang termuat dalam ‘Book of Rites’ (Kitab Ritual), juga dianggap sebagai ‘suara’ autentik dari Sang Guru. Kontur dari transmisi ajaran Confusian dari Sang Guru melalui murid yang ia ajar secara langsung hingga ke generasi cucu, yang diyakini sebagai penulis dari ’Doctrine of the Mean’ (Doktrin Makna), telah menjadi jelas dan iklim opini di mana Analek dianggap telah dikumpulkan tidak lagi menjadi sebuah misteri. Kita masih jauh dari keyakinan absolut tentang pencitraan Konfusius yang dihasilkan oleh berbagai persepsi para pengikutnya, tapi kita relatif lebih yakin bahwa kita tidak lagi berhubungan dengan ingatan-ingatan yang dibuat-buat.
Versi terbaru dari Analek, yang diperkaya oleh pengetahuan selama berabad-abad, merupakan endapan yang terdiri atas berbagai lapisan linguistik, folologis, sastra, dan tradisi tekstual, yang memungkinkan untuk munculnya berbagai pujian dan celaan, penggunaan dan penyalahgunaan, penghargaan dan ketidaksetujuan, serta pemahaman dan kesalahpahaman. Untuk sampai pada keyakinan, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mempelajari Analek, akan tetapi kemungkinannya terbatas. Sugesti bahwa ada banyak interpretasi yang sah sebanyak orang yang berminat untuk membuat interpretasi merupakan tindakan membesar-besarkan yang mustahil untuk dilakukan. Faktanya, hanya sedikit komentar signifikan yang tetap selamat setelah berabad-abad dilakukannya tradisi komentarial. Meskipun terdapat kemajemukan dalam strategi interpretasi, relativisme juga tidak berlaku baik dalam teori atau dalam praktik. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa teks Analek bersifat sangat fleksibel untuk mendorong munculnya perbedaan, bahkan bacaan yang perbedaannya radikal.
Seperti kitab Perjanjian Baru dan dialog Socrates, Analek merupakan sumber inspirasi bagi mereka yang menghargai pengalaman melihat dan mendengar ajaran-ajaran Sang Guru secara langsung. Seperti yang telah diutarakan oleh beberapa ilmuwan, Bab 10 menyajikan penggambaran yang halus dan penuh nuansa dari cara Konfusius berpakaian, berjalan, mendekati orang yang lebih tua/terhormat, menemui orang asing, dan menemui teman. Memang, ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta di atas semua itu, performa ritualnya digambarkan secara jelas. Rutinitas hariannya yang penuh konteks juga menunjukkan kewajaran yang ia tunjukkan di sebuah situasi khusus. Di mata para muridnya, apa yang ia lakukan membangkitkan sebuah nilai estetika akan keanggunan. Ia ada dalam kekonkretan yang hidup dan bukan dalam keabstrakan yang universal. Bahkan, setelah dua puluh lima abad ketiadaannya, telinga yang terlatih masih tetap bisa mendengar suara Sang Guru dalam dirinya, serta bisa merasakan kehadirannya. Kepribadian Konfusius yang penuh kehidupan, yang juga telah membuatnya sangat manusiawi, diperlihatkan dengan sangat jelas.
Sebagai percakapan yang telah tecerna serta pembahasan yang telah dipersingkat, metode dialog memenuhi Analek. Di permukaan, Konfusius, sebagai guru, hanya memberikan jawaban. Para siswanya yang datang kepadanya untuk mencari panduan, pengetahuan serta kebijakan. Di sini, tidak banyak ruang untuk adanya negosiasi. Komunikasi dua arah tidak terlihat sama sekali. Kita hampir tidak pernah menemukan murid yang mempertanyakan ajaran Sang Guru. Bahkan dalam kasus Zilu yang menunjukkan ketidaksetujuannya yang jelas terlihat saat Sang Guru memutuskan untuk mendatangi wanita bangsawan yang tengah bermasalah, tidak ada penjelasan yang diberikan kecuali bahwa ia tidak bersalah [6:28]. Mungkin para murid tersebut sangat takjub hanya oleh kehadiran Konfusius sehingga mereka hanya mendengarkannya ajaran yang ia berikan dengan seksama. Kasus Yan Hui sangat relevan dengan hal ini. “Guru mengatakan, ‘aku bisa berbicara sepanjang hari kepada Yan Hui—ia tidak akan keberatan, dan ia akan terlihat bodoh. Akan tetapi lihatlah Yan Hui ketika ia sendiri: semua tindakannya mencerminkan apa yang telah ia pelajari. Tidak, Yan Hui tidaklah bodoh!’” [2:9]. Sebagai respons, Yan Hui, yang dikenal sebagai salah satu murid Konfusius yang paling terpandang, sangat menghormati Konfusius sebagai seorang guru.
Yan Hui mengatakan setengah mengeluh: “semakin aku merenung- kannya, semakin tinggi ia berada; semakin dalam aku menggali, semakin ia tak mau keluar; aku melihatnya di depan mataku, lalu tiba- tiba ia telah berada di belakangku. Selangkah demi selangkah guru kami benar-benar tahu caranya menjerat orang. Ia merangsangku dengan kesusastraan, ia mengendalikan aku dengan ritual. Bahkan jika aku ingin berhenti, aku tidak akan bisa. Saat semua energiku telah habis, tujuanku terlihat jelas di depanku. Aku ingin merengkuhnya, tapi aku tak tahu caranya” [9:11].
Yang mendasari kedua pernyataan ini adalah pemikiran asumtif bahwa pengajaran dengan keteladanan, alih-alih hanya dengan kata- kata, akan menuntun para murid untuk sampai pada kesadaran akan diri mereka sendiri. Pertentangan tidaklah dianjurkan, karena ‘kata- kata yang tajam’ bukanlah tanda-tanda kebajikan [1:3]. “Apa gunanya kefasihan lidah? Lidah yang tangkas hanya akan menciptakan musuh” [5:5; Simon Leys, terjemahan, The Analek of Konfusius (New York: W. W. Norton & Company, 1997), p. 19]. Memang, ‘pembicaraan yang fasih’ seperti “kepura-puraan dan kata-kata untuk menjilat,” harus dihindari [5:25]. Seni mendengarkan, yang sangat penting bagi pengetahuan pribadi, harus diolah sebagai syarat dari keanggunan ekspresi verbal. Gaya pengajaran Confusian, bila dikontraskan dengan metode Socrates, lebih mengutamakan pemahaman dari pengalaman dan apresiasi bisu.
Proses belajar (xue), yang sangat menonjol dalam Analek, melibatkan praktik sekaligus kognisi. Proses belajar merupakan proses latihan spiritual. Seseorang tidak hanya belajar dengan hati dan pikirannya (xin), akan tetapi juga dengan badannya (shen). Refleksi Zengzi tentang pengolahan kesadaran dirinya sangat berkaitan di sini: “saya menelaah diri saya sendiri tiga kali dalam sehari. Saat berbuat sesuatu bagi orang lain, apakah aku sudah bisa dipercaya? Dalam berhubungan dengan teman-teman, apakah aku sudah setia? Sudahkah aku menjalankan apa yang diajarkan kepadaku?” [1:4]. Proses belajar meliputi proses perubahan pada badan dan juga pencerahan pada pikiran. Sebagai praktik dari ‘enam seni’ (ritual, musik, memanah, keahlian berkuda, kaligrafi, dan aritmatika), proses belajar jelas menunjukkan bahwa disiplin fisik dan mental sama-sama diperlukan dan bahwa proses berpikir dan belajar (si) seharusnya saling melengkapi satu sama lain [2:15].
Yang tersirat dalam pendidikan model ini adalah adanya komunitas yang dipercaya, atau sebuah komunitas berbasis kepercayaan. Persaudaraan antarorang-orang dengan kesamaan pikiran yang dibentuk oleh Konfusius dan murid-muridnya merupakan persaudaraan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia melalui pendidikan. Para sejarawan modern menginterpretasikan deskripsi tradisional akan Konfusius sebagai ‘Guru Pertama’ (xianshi) dalam ranah peran sosialnya, yaitu bahwa ia merupakan cendekiawan pertama yang mendirikan sekolah swasta di Cina. Meskipun berbagai lembaga pembelajaran yang didirikan oleh pemerintah telah berdiri sejak berabad-abad sebelumnya, Konfusius merupakan inovator dari sekolah swasta mandiri. Terdapat satu referensi tentang metode pembayaran sederhana (biaya pendidikan) di Analek [7:7], akan tetapi para murid yang datang ke Konfusius, seperti para pengikut Yesus, bukanlah anak-anak tapi para orang dewasa yang merupakan pencari kebenaran, yang bersemangat dan berjuang untuk memahami makna hidup. Mereka tertarik pada Konfusius karena visinya yang besar dan pengertiannya yang mendalam akan misi. Sifatnya yang seolah bersinar dan tanpa pretensi pasti telah menjadi sumber inspirasi bagi mereka. “ Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan diam-diam, untuk selalu lapar akan belajar, dan untuk mengajari orang lain tanpa lelah— semua ini datang kepadaku secara alami.” [7:2; Leys, hal. 29].
Konfusius mungkin tidak memiliki serangkaian kurikulum, akan tetapi Analek memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung fakta bahwa tujuan pendidikan Konfusius adalah pembelajaran untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Adalah tidak mengherankan jika, di bawah pengaruh ‘guru pertama’, tujuan utama pendidikannya adalah pembangunan karakter manusia di Asia Timur. Apa maksudnya? Para pemikir Neo-Confusian menginterpretasikannya sebagai ‘pem- belajaran untuk diri sendiri,’ ‘pembelajaran akan tubuh, hati serta pikiran,’ ‘pembelajaran akan hati dan pikiran serta hakikat manusia,’ ’pembelajaran akan hakikat manusia dan takdir,’ ‘pembelajaran akan kearifan,’ dan ‘pembelajaran menjadi manusia terhormat’ (junzi, ‘manu-sia yang mulia,’ ‘manusia yang utama,’ atau ‘orang yang berilmu men- dalam’). Konfusius membuat banyak referensi mengenai ide tentang manusia terhormat. Sekilas, pembelajaran untuk menjadi orang yang terhormat tidaklah terlihat sulit: orang terhormat kalau makan tidak sampai terlalu kenyang, ia memilih tempat tinggal tanpa menuntut kenyamanan, ia rajin dalam bekerja dan bijak dalam berkata-kata, ia berteman dengan orang yang bermoral untuk menguatkan cara-cara hidupnya. Orang seperti itulah yang disebut sebagai orang yang senang belajar [1:14; Leys, hal. 5].
Dengan menggambarkan orang terhormat sesuai dengan gambaran dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, Konfusius menjelaskan bahwa salah satu sifat yang membedakan orang terhormat dengan orang lain adalah sikap dan tindakannya. “Orang terhormat pelan dalam berbicara dan cepat dalam bertindak” [4:24, Leys, hal.17] dan “ia mengajarkan hanya apa yang ia lakukan” [2:13, Leys, hal.7]. Ia menegakkan kebajikan dan keadilan [4:11] dan ia selalu berpihak pada kebenaran dalam semua urusannya di dunia [4:10].
Akan tetapi, Konfusius juga mengingatkan, “seseorang yang yang tidak membumi menunjukkan bahwa ia tidak memiliki otoritas dan pembelajarannya akan selalu dangkal. Orang terhormat menjunjung tinggi ketaatan dan kesetiaan di atas yang lain: ia tidak berteman dengan orang-orang yang bermoral buruk. Saat ia berbuat kesalahan, ia tidak takut untuk mengubah cara dan tindakannya.“ Pembelajaran untuk diri sendiri [14:24] sangat relevan untuk diterapkan di sini. Orang terhormat memperluas pengetahuannya dengan membaca literatur dan menjaga dirinya dengan melakukan ritual [12:15]. Ia santai tanpa harus menjadi sombong [13:26]. Ia bisa memancing kebaikan pada orang lain [12:16]. Mudah bekerja untuknya, tapi sulit untuk membuatnya puas; karena, meski ia tidak pernah meminta kita melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita, ia tidak akan senang jika kita tidak mengikuti ‘The Way’ [13:25]. Saat Zilu bertanya: “seperti apakah orang yang pantas disebut sebagai orang terhormat itu?” Sang Guru menjawab, “yaitu orang yang, di satu sisi bersungguh-sungguh dan baik hati, dan di lain pihak ia juga ramah; ia lah yang berhak untuk disebut sebagai orang terhormat— bersungguh-sungguh dan baik hati kepada teman-temannya, serta ramah kepada saudara-saudaranya.” [13:28, D.C. Lau, terjemahan Konfusius—Analek, Penguin Classics, 1979, hal. 123].
Edward Shill menuturkan bahwa Konfusius mungkin merupakan pencipta dari ide ‘kebudayaan’ modern. Orang-orang terhormat versi Konfusius telah berbudaya dan madani. Meskipun Konfusius, yang juga merupakan pemanah hebat dan ahli dalam berkuda, yang menyukai berburu dan memancing, ia lebih memilih untuk memupuk keterampilan seni sebagai ekspresi dari sifat ideal yang ia agung-agungkan. Sebagai orang yang gemar berolah raga, ia menyukai memanah. “Orang terhormat menghindari kompetisi. Tapi, jika ia harus berkompetisi, maka ia akan memanah. Dalam memanah, saat ia membungkuk dan bertukar rasa hormat sebelum bertanding dan saat acara minum- minum setelahnya, ia tetap menjadi orang yang terhormat, bahkan saat dalam pertandingan. [3:7, Leys, hal. 11]. Sebagai orang yang tidak pernah lelah berjalan, Konfusius menunjukkan keberanian yang besar dalam berbagai petualangannya yang berat dan berbahaya, akan tetapi dalam situasi normal, ia selalu “hangat, baik hati, penuh rasa hormat, bersikap biasa, dan berbeda” [1:10].
Konfusius hidup di era ketidakteraturan politik serta carut-marut sosial. Tradisi ritual yang rumit (fengjian, sistem feodal), yang diperkuat oleh Bangsawan Zhou, salah satu negarawan yang paling berpengaruh saat itu, menjadi tidak berfungsi. Perang internal bergejolak antarnegara bagian. Beberapa pertapa mencoba meyakinkan Konfusius untuk menarik diri dari dunia luar dan menikmati kehidupan yang tenang dan damai dengan bercengkerama dengan alam. Sang Guru, meskipun tetap menghormati pilihan filosofi tersebut, tetap teguh dengan pilihan dan tindakannya: “Aku tidak bisa hanya berteman dengan burung dan binatang buas. Bukankah aku adalah anggota ras manusia? Jadi, siapa yang harus aku jadikan teman? Jika semua orang di dunia mengikuti ‘The Way’, aku tidak akan lagi harus mereformasinya” [18:6]. Makanya, tidak mengherankan jika di antara agama-agama dalam sejarah dunia (Yahudi, Buddha, Jainisme, Daoisme, Kristen, dan Islam), Konfu- sianisme bersifat unik karena ia membedakan antara kesucian agama dan sekularisme.
Terus terang, buku seminar Herbert Fingarette yang mencoba mengarakterisasikan bahwa Konfusius telah menganggap sekularisme sebagai kesucian agama salah arah. Konfusius tidak menempatkan tempat spiritual (gereja, pura, sinagoga, biara, atau asrama) sebagai tempat suci untuk melakukan kontemplasi, meditasi, berdoa, dan beribadah. Ia juga tidak menyatakan adanya tanah suci atau tempat lain yang berbeda dengan tempat tinggal kita sehari-hari. Dengan komitmen untuk mengubah hidup manusia dari dalam diri mereka sendiri, ia mau tidak mau tersangkut dalam urusan politik di masa itu. Akan tetapi, adalah salah untuk mengatakan bahwa fokus utama Konfusius adalah politik dan bukan pengajaran.
Di mata para muridnya, Sang Guru nampak selalu disibukkan oleh berbagai pemikiran tentang pemerintahan dan selalu prihatin dengan kurangnya akses akan otoritas politik. Ia selalu yakin akan kemampuannya untuk menciptakan ketertiban ritual baru, jika saja ia diminta oleh penguasa untuk melakukannya [13:10; 17:5]. Akan tetapi, ia tetap memiliki ide tentang bagaimana orang terhormat seharusnya bersikap sebagai pegawai pemerintah yang juga gemar belajar, dan ia juga sangat kritis terhadap politisi masa itu.
Zigong bertanya: “seperti apakah orang yang layak untuk disebut sebagai orang terhormat itu?” Sang Guru menjawab: “yaitu orang yang penuh rasa hormat dalam bersikap, yang dikirim ke empat penjuru angin di dunia, dan tidak mempermalukan tuannya, ialah yang layak untuk disebut sebagai orang yang terhormat.” “Dan setelah itu, jika aku boleh meneruskan bertanya?” “Keluarganya memuji ketinggian baktinya kepada orang tua, dan orang-orang di desanya memuji rasa hormatnya pada para tetua.” “Kata-katanya bisa dipercaya, apa pun yang ia lakukan, ia akan selalu menyelesaikannya. Mungkin ia hanya menunjukkan sifat keras kepala dari seorang manusia, akan tetapi, ia masih berhak untuk dimasukkan dalam kategori manusia terhormat meski di tingkat terendah.” “Dalam hal ini, bagaimana menurut anda tentang para politisi kita?” “Aduh, makhluk kerdil ini bahkan tidak layak untuk kubahas.”
Bahkan jika kita meyakini bahwa panggilan jiwa Konfusius merupakan pengajaran dan bukan politik, kita harus meyakini bahwa karena ia mengasumsikan politik sebagai ekstensi dari etika, baginya, pembelajaran akan moralitas personal merupakan persyaratan utama sebelum orang berpartisipasi dalam politik. Politik, dalam hal ini, bukan berarti sebagai kemampuan untuk memanipulasi kekuasaan, otoritas dan pengaruh. Ia juga bukan berarti penggunaan taktik dan strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi, ia merujuk pada pemerintahan yang adil dan efisien yang bisa tercapai melalui seni kepemimpinan berdasarkan moral: “kekuasaan yang berdasarkan ke- bajikan bisa diilustrasikan sebagai Bintang Kutub yang mengatur ribuan bintang lain tanpa harus meninggalkan tempatnya” [2:1, Lau, hal. 63].
Untuk mewujudkan ide tentang pemerintahan ini, cara yang benar bagi pemerintah adalah dengan tanpa menggunakan paksaan dan kekerasan: “kekuatan moral dari orang terhormat adalah angin; sementara kekuatan moral dari orang biasa adalah rumput. Saat ada angin, rumput harus merunduk” [5:8, Leys, hal. 58]. Gambaran tentang tunduknya rumput secara alami kepada angin yang semilir bukanlah dengan cara memaksakan kekuasaan, akan tetapi seperti tarian ritual yang senada dengan irama. Dalam konteks ini, meskipun pemerintah merupakan alat yang efektif untuk mengartikulasikan kepemimpinan moral, ia bukan satu-satunya arena yang penting.
Fitur yang menonjol dari gaya pemerintahan Konfusius adalah etika keluarga yang menjadi pusat dari signifikansi politik: “seseorang bertanya kepada Konfusius: “Guru, kenapa Anda tidak bergabung dengan pemerintahan?” Sang Guru menjawab, “dalam kitab ‘The Document’ (Shujing) dikatakan, pupuklah rasa bakti kepada orang tua dan berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu, begitulah caramu untuk berkontribusi terhadap politik. Ini juga bisa disebut sebagai salah satu bentuk politik, tanpa harus bergabung dengan pemerintahan” [2:21, Leys, hal. 8]
Selanjutnya, berbagai teori dan praktik Konfusius tentang pemerintahan yang humanis secara fundamental berbeda dengan cara berpolitik dari ‘makhluk-makhluk kerdil’ tersebut,’ Ia tidak mau merendahkan dirinya sendiri dengan memainkan permainan mereka. Tujuannya melakukan berbagai aktivitas politik adalah untuk memastikan bahwa ‘The Way’ akan tetap dijalankan. Metode yang ia pilih adalah dengan menjawab berbagai masalah fundamental dari politik sebagai prasyarat untuk pemerintahan dan manajemen. Ia meyakini bahwa jika masalah-masalah fundamental ini diangkat sebagai latar belakang dunia politik, tidak akan ada lagi politik yang hanya berupa nama. Lalu, apa yang disebut sebagai politisi? Dengan memakai homonim, ia mendefinisikan politik (Zheng) sebagai ‘perbaikan’ (Zheng), yang berarti bahwa politik utamanya merupakan kepemimpinan. Jika pemimpin tidak memperbaiki dirinya sendiri sebagai pelayan publik, kualitas pemerintah akan terkikis dan performa pemerintah akan rusak, bahkan meski lembaga-lembaga yang diperlukan sudah tersedia
Teorinya yang terkenal tentang “perbaikan nama” samar-samar terlihat sederhana: Bangsawan Jing dari Qi bertanya kepada Konfusius tentang pemerintah, ia menjawab: “biarkan yang menjadi tuan tetap menjadi tuan, hamba tetap menjadi hamba, ayah tetap menjadi ayah, anak tetap menjadi anak.” Si Bangsawan menjawab: “Bagus! Karena jika tuan tidak menjadi tuan, hamba tidak menjadi hamba, ayah tidak menjadi ayah, dan anak tidak menjadi anak, aku tidak akan bisa yakin tentang apa pun lagi—bahkan tentang makanan sehari-hariku” [12:11, Leys, 57]. Yang tersirat dari pernyataan ini adalah keyakinan bahwa meskipun makanan yang cukup, senjata yang cukup, dan kepercayaan rakyat sama pentingnya bagi perdamaian dan kesejahteraan suatu negara, akan tetapi kepercayaan rakyat adalah yang terpenting. Jangan sampai kita berpikir bahwa bentuk-bentuk moralisasi politik Konfusius sebagai ide yang tidak dapat dipertahankan, langkah-langkah realism-ah yang memandu pendekatannya menuju struktur kekuasaan di era saat itu.
Pendeknya, ia tidak memiliki ilusi tentang real politik. Ia terus- menerus menilai situasi secara keseluruhan dan mencoba dengan keras untuk mencari kesempatan agar ditunjuk secara politis. Ia sangat siap untuk menghadapi kompleksitas situasi politik dan berharap bahwa dengan bantuan para muridnya yang dianggap mampu, ia bisa berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Adalah bukan ketidaksengajaan jika di antara para muridnya, terdapat mereka yang memiliki keterampilan tinggi dalam mengatur negara: baik untuk urusan ritual, musik, keuangan, diplomasi, dan militer. Akan tetapi, ia tidak akan pernah mengorbankan prinsip-prinsipnya akan manfaat dan ia selalu mengikuti komitmennya bahwa kesejahteraan rakyat merupa- kan pembenaran utama dari pemerintahan yang humanis (renzheng).
Sepertinya terlihat jelas bahwa Konfusius merupakan seorang politisi yang gagal, meskipun awalnya ia diterima dengan sopan dan penuh rasa hormat di hadapan para bangsawan yang berkuasa, ia tidak berhasil mendapatkan posisi untuk mewujudkan pengaruhnya dan pada akhirnya ia terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Kegagalannya usahanya untuk menyetir para penguasa agar menjauhi intrik-intrik politik yang hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaan seperti mengindikasikan bahwa ia tidak terlalu cakap dalam memainkan intrik-intrik politik. Ia mungkin menjadi pahlawan yang tragis di mata para sejarawan simpatik yang meyakini, seperti yang juga diyakini oleh Konfusius, bahwa ia mungkin bisa sedikit mengembalikan ketertiban politik dari Dinasti Zhou yang megah, seandainya ia diberi kesempatan untuk menunjukkan keterampilan kenegaraannya [17:5]. Akan tetapi, jika kita hanya menilai pemahaman diri Konfusius hanya dengan situasi politik saat ini, maka kita telah salah. Karena, persepsinya tentang ‘politik’ sebagai ‘perbaikan’ melibatkan pengetahuan, budaya, moralitas, dan rasa. Hal tersebut merupakan sebuah visi akan komunitas yang sarat dengan implikasi epistemologi, etika, dan estetika.
Kita telah membahas observasi Konfusius bahwa kepatuhan untuk meninggalkan kewajiban keluarga seseorang merupakan sebuah kasus bonafid dari sebuah keterlibatan politik. Dalam pandangannya, proses politik dimulai dari rumah, ia tidak terpisah dari cara hidup seseorang. Yang tersirat dari gaya praktik-praktik Konfusianisme adalah pembentukan komunitas melalui usaha pemahaman diri dan pembelajaran bersama. Para penganut ajaran Konfusius ini terdiri dari para pria dewasa yang sadar akan kapasitas diri mereka untuk ikut serta dalam memahami permasalahan di dunia. Mereka juga secara sadar memutuskan untuk ikut andil dalam diskusi umum guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Solidaritas grup yang terbentuk bukan merupakan hasil paksaan dari Sang Guru ataupun model pedagogi yang sudah ada sebelumnya. Solidaritas ini juga bukan seperti para pengikut Maoisme yang berlandaskan pada kepentingan politik dan fungsi etika semata.
Para penganut ini berkumpul dengan Konfusius demi mengem- bangkan potensi diri terhadap keluasan ilmu pengetahuan, keragaman budaya, etika, dan keluasan kontribusi diri terhadap kebenaran umum. Pemikiran konstruktif ini membantu mereka untuk lebih memberdayakan diri sendiri dan mengembangkan sikap saling meng- hormati serta menghargai antarsesama manusia. Konfusius membekali mereka dengan satu pemahaman bahwa manusia bukanlah alat yang hanya bekerja secara fungsional [2:12], namun manusia harus menjadi junzi (manusia yang berbudi luhur, bermartabat, bersifat pemimpin dan penyayang) seutuhnya, yang mampu mengambil tindakan politik pada berbagai level kehidupan dan dalam kondisi yang beraneka ragam.
Pola hubungan antara Konfusius dengan murid-muridnya menun- jukkan bahwa kerja sama yang mereka jalin belum pernah ada dalam sejarah bangsa Cina sebelumnya dan sangat unik bila dibandingkan dengan sejarah-sejarah keagamaan besar lain sebelumnya. Konfusius bukanlah penemu dari tradisi keilmuan Konfusius yang secara luas dipelajari oleh para pengikutnya. Adalah bukan sebuah bentuk keseder- hanaan apabila Konfusius mengaku dirinya sebagai ‘perantara’, bukan sebagai ‘penemu’ [7:1]. Dia bukan juga sebagai manifestasi tertinggi dari nilai kemanusiaan yang selalu dikagumi oleh para muridnya. Sekali lagi, bukan karena alasan kesederhanaan diri jika Konfusius menolak untuk disebut sebagai seseorang yang bijaksana dan humanis (ren) [7:34]. Potret kesederhanaan Konfusius yang tidak dibuat-buat, justru menjadikannya sebagai seseorang yang berpengaruh besar terhadap para muridnya. Sumber inspirasinya berasal dari bentuk-bentuk kehidupan yang kaya, yang berasal dari suatu konsep waktu dan tempat yang spesifik. Walaupun berakar dari waktu dan tempat yang spesifik, isi dari falsafah hidup Konfusius merupakan hal-hal yang bersifat umum yang memiliki peran penting secara universal.
Karena Konfusius menganggap dirinya sebagai penjaga kehidupan dan perkembangan manusia, dia menjalin hubungan baik dengan orang-orang bijak dan berpengaruh yang mengatur hajat hidup dan tradisi kumulatif orang banyak; dia tidak terlalu memfokuskan ajarannya pada konsep abstrak di luar pemahaman manusia umumnya ataupun evolusi alam tanpa pengaruh atau campur tangan manusia. Bangsawan Zhou, orang yang sangat berpengaruh pada masa itu, yang bertanggung jawab dalam pengaturan masalah politik pada Dinasti Zhou, merupakan model paradigma akan sifat yang dijadikan model oleh Konfusius. Mimpi terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali dan mengaplikasikan maha karya sistem politik Zhou pada masa kini untuk mencapai perdamaian dunia berdasarkan prinsip pengembangan diri, penumbuhan rasa simpati, keadilan, dan tanggung jawab. Walaupun Zhou memiliki prestasi yang gemilang, ia menganggap dirinya hanya sebagai ‘perantara atau penyampai’ dan bukan ‘penemu’, seperti halnya yang diyakini dan dilakukan oleh Konfusius. Zhou telah mewarisi kejayaannya dari raja-raja bijaksana terdahulu, seperti: Yao, Shun, Yu, Tang, Wen, dan Wu. Kesadaran sejarah Konfusius terbentuk dari kesadaran dirinya akan norma adat yang bisa dan seharusnya dilestarikan sebagai bagian dari misi sebagai seorang ‘terpilih’ dalam melaksanakan tugas tersebut.
Sepanjang perjalanan Konfusius dari satu daerah ke daerah yang lain dalam usaha pencarian pemimpin yang bisa memberikan kesempatan untuk merealisasikan impiannya, tanpa sengaja, terbentuklah kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman sama, yang disebut sebagai komunitas diskusi. Apabila ditinjau kembali, walaupun ia tidak bisa menanamkan idealismenya pada suatu model pemerintahan secara praktis, realita sosial yang ia tawarkan dan diskusikan dalam kelompok-kelompok tersebut ternyata bermanfaat. Persahabatan, sebagai usaha kolaboratif yang ia ciptakan bersama dengan murid-muridnya, bersifat terbuka, fleksibel, komunikatif, interaktif, inklusif, dan saling menguntungkan. Konfusius berinteraksi dengan muridnya bukan sebagai seorang filusuf yang secara metodis mengajarkan inti dari sesuatu selangkah demi selangkah. Tidak pernah ada bukti kesusastraan yang menunjukkan adanya proses penalaran rumit dalam dialog-dialog Sokratik. Nasihat Konfusius hanyalah disampaikan dalam bujukan verbal, tutur kata yang fasih, dan diplomasi ekspresi yang pandai. Walaupun Konfusius menghargai kecakapan diplomasi, ketajaman pemikiran dan kemampuan berartikulasi dalam karya sastra, ia lebih memilih apresiasi yang disampaikan dalam diam, seperti pada kasus Yan Hui, untuk memberikan argumen yang lebih efektif. Kasus ini mengingatkannya akan kelicikan masalah hukum dan penyelesaian suatu perkara. Pada kasus sipil, ia lebih memilih negosiasi, mediasi, atau penyelesaian masalah di luar pengadilan daripada harus menempuh jalur formal, tidak jelas, dan menempuh mekanisme kontrol yang penuh paksaan.
Masyarakat sosial ideal yang di gambarkan oleh Konfusius dan komunitas diskusi yang dia bentuk melalui pengajaran percontohan, kesemuanya adalah kegiatan yang bersifat sukarela. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memfasilitasi pertumbuhan kesadaran diri dari setiap anggotanya. Sistem pemerintahan berdasarkan pandangan sosial seperti ini membutuhkan berbagai bentuk refleksi diri, baik dalam bidang politik atau kecerdasan berpikir serta prosedur pelaksanaan yang efektif yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan yang humanis. Bukan sesuatu yang baru apabila Konfusius berpendapat bahwa para pemimpin yang mengaplikasikan paham pengembangan diri ini selayaknya mengarahkan kekuasaan pengawasannya dalam dua proses yang seimbang, yaitu: kesadaran diri yang bertanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan yang teliti yang bisa menjamin kehidupan masyarakat dan manusia pada umumnya. Permasalahan pokok dari suatu negara, seperti halnya pertanian, kemiskinan, dan masalah kebutuhan pokok lainnya harus ditangani secara serius dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Berbanding terbalik dengan pengertian yang diutarakan oleh Hegel, bahwa kedaulatan suatu negara ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin. Kedaulatan layak dipegang oleh rakyat, seperti halnya telah tercantum dalam Amanat dari Tuhan. Pemimpin suatu negara adalah orang yang dipercaya sebagai pelaksana mandat, yang bertanggung jawab memelihara kepentingan moral sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyatnya.
Rakyat, pada hakikatnya bukanlah manusia yang lalai dan menderita. Tradisi yang diadopsi dalam paham Konfusius menjelaskan bahwa rakyat mempunyai tanggung jawab untuk menumbuhkan budaya kebijaksanaan. Hal ini sejalan dengan konsep pemimpin sebagai ‘ayah dan ibu’ dari rakyat. Mencius, sejalan dengan pemikiran Konfusius, berpendapat bahwa jika pemimpin gagal dalam melaksanakan tugasnya (pemimpin harus bertindak sebagai pemimpin), para menteri berkewajiban untuk memprotesnya. Apabila protes yang diajukan tidak ditanggapi, mereka harus menyatakan ketidaksetujuan tersebut secara keras. Dalam kondisi yang luar biasa, membunuh pemimpin bisa diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip ‘mengembalikan nama baik’. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab dianggap sebagai pemimpin yang tidak memiliki kekuatan, kewenangan, dan kekuasaan. Ia bisa dihilangkan atau dibunuh demi kepentingan rakyat. Rakyat adalah air, mereka bisa memberikan dukungan terhadap suatu kapal, mereka juga bisa menenggelamkannya. “Tuhan melihat apa yang dilihat oleh rakyat dan Tuhan mendengar apa yang didengar oleh rakyat”, pandangan ini bukan sesuatu yang abstrak, tetapi dianggap menjadi paham praktis yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kebulatan tekad Konfusius untuk mengubah pandangan politik melalui kekuatan mental, nilai budaya, kekompakan sosial, dan kesadaran akan sejarah bangsa sering dipandang secara keliru sebagai semangat yang naif dari pengetahuan politik awam. Pemahaman ini juga disebut sebagai persepsi politik yang bertujuan untuk mengembangkan diri manusia. Politik selalu melibatkan kekuasaan, pengaruh, dan kewenangan bernegara; akan tetapi, tujuan politik dalam ranah Konfusius adalah pembelajaran etika melalui pendidikan. Pengaturan keamanan dan pemerataan pendapatan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi lebih berperan sebagai prasyarat untuk mencapai perkembangan kemanusiaan. Perintah Konfusius bahwa “dari pemimpin sampai rakyat jelata, semua harus memandang pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai akar dari prinsip kehidupan” yang sudah seharusnya berfungsi sebagai dasar menjadikan masyarakat madani daripada harus menerapkan sistem kontrol sosial yang meresahkan. Disadur dari istilah yang dipakai Emile Durkheim, Konfusius membawa paham solidaritas organik melalui proses saling memahami dan menumbuhkan kesadaran diri yang koorporatif. Beberapa penganut Konfusianisme berprofesi sebagai ahli sastra, petani, pengrajin, tentara, pedagang, dan praktisioner dari berbagai macam profesi. Keanekaragaman profesi ini memperkaya dan mempererat tali persahabatan komunitas Konfusius yang bisa dilihat dari kekayaan latar belakang dan keanekaragaman orientasi kehidupan.
Semangat demokrasi yang secara implisit terinspirasi dari H.G. Creel, seorang Profesor dari Chicago dan dekan fakultas Sinologi tahun 1950an, tersirat dalam ajaran Konfusius yang bersifat demokrasi liberal dan mengajarkan kemanusiaan rasional. Adalah berlebihan apabila Konfusius dianggap sebagai jiwa atau ruh dari ajaran tersebut, karena ide pokok dari ajaran demokrasi liberal telah diadopsi oleh Konfusius dari sejarah sebelumnya, dan bukan merupakan ciptaannya sendiri. Ide tentang pemerintahan demokrasi liberal ini telah menjadi salah satu ide yang diajarkan Konfusius. Akan tetapi, yang perlu di garis bawahi adalah yang disebut Konfusius sebagai interaksi kemanusiaan yang tepat, yang seharusnya melebihi kategori-kategori politik modern, meskipun kategori tersebut sangat luas. Dalam versi terfragmentasi dari sebuah minat dan skema terpisah dari disiplin profesional, pemunculan ide persatuan secara ‘organik’, dan bukan ‘mekanik’, seperti halnya konsep persaudaraan universal, dianggap hanya khayalan belaka. Para ahli teori akademik modern, yang bergerak di bawah pengaruh bidang keahlian dan profesionalitasnya, kesulitan untuk menemukan rasa utuh yang merupakan wujud dari pencarian jati diri manusia yang sesungguhnya. Kekerabatan yang dirasakan oleh Konfusius dan para pengikutnya bukan hanya sebuah konkretisasi dari aspirasi manusia pada umumnya. Kharisma Konfusius terletak pada kekuatan magnetisnya untuk menarik para pengikut yang bersemangat dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Mereka mau saling berbagi ilmu, visi dan misi untuk mengubah dunia dari dalam diri mereka dengan menyentuh ranah mental dan fisik dari setiap manusia guna mencapai seni pengembangan diri. Teori pengembangan diri Konfusius ini jauh lebih rumit dari pencarian jati diri pribadi menyangkut nilai-nilai spiritual, karena teori ini bersifat multi-dimensional. Teori ini tidak hanya membahas tentang tubuh dan pemikiran manusia, tetapi juga tentang lingkungan total di mana manusia berada. Gambaran yang dilukiskan Konfusius tentang perjalanan spiritualnya adalah sebagai berikut:
-
- Pada usia lima belas tahun, saya memutuskan untuk belajar, pada usia tiga puluh tahun, saya mengambil sikap hidup, pada usia empat puluh saya tidak lagi mempunyai khayalan. Pada usia lima puluh tahun, saya memahami Perintah Tuhan, pada usia enam puluh saya menyelaraskan pendengaran saya (dengan lingkungan). Pada usia tujuh puluh, saya bisa mengikuti keinginan hati saya tanpa melanggar aturan apa pun [2:4]
Catatan biografi singkat ini telah menginspirasi berbagai macam interpretasi. Pada kenyataannya, Konfusius hidup dengan suatu pema- haman diri bahwa dia dulunya adalah seorang pelajar juga: “Di sebuah dusun yang terdiri hanya 10 pemukiman penduduk, kamu pasti bisa menemukan orang yang setia dan berbakti seperti aku, tapi kamu tidak akan menemukan seseorang yang suka belajar melebihi diriku” [5:28; Leys, hal.23].
Sepanjang hidupnya, Konfusius selalu berusaha mengembangkan dirinya. Ia sadar apabila kebijaksanaan atau kesempurnaan moral mustahil ia dapatkan; ia belajar tanpa putus asa dan mengajar tanpa lelah [7:34]. Ia mencoba segala kemungkinan untuk belajar: “taruhlah aku bersama dengan dua orang teman yang kamu pilih secara acak - mereka akan selalu mempunyai sesuatu untuk diajarkan padaku. Aku bisa mempelajari kemampuan mereka sebagai contoh dan kekurangan mereka sebagai peringatan untuk lebih waspada” [7:22; Leys, hal. 31]. Ia dengan terbuka mengakui bahwa ia harus mendapatkan kebijaksanaan kumulatif dari masa lampau untuk membuatnya menjadi lebih bijaksana: “Aku bukan terlahir dari ilmu pengetahuan, tetapi karena ketertarikanku terhadap keunikan ilmu pengetahuan, Aku bisa dengan cepat mencari dan mempelajarinya” [7:20; Lau, hal. 88]. Ia sangat sadar bahwa ia tumbuh dari upaya pengembangan potensi dirinya: “kegagalan dalam menumbuhkan kekuatan moral, kegagalan dalam mencari hal yang sudah pernah aku pelajari, ketidakmampuanku untuk membela apa yang aku anggap benar dan ketidakmampuanku untuk memperbaiki yang salah - beberapa hal inilah yang selalu aku khawatirkan” [7:3; Leys, hal. 29]. Singkatnya, Konfusius adalah seorang pembelajar yang saking ‘antusiasnya’ ia sampai lupa untuk makan, dalam kesenangannya belajar, ia lupa untuk khawatir, dan ia tidak mengindahkan pendekatan tradisional” [7:19; Leys, hal.31].
Isi pembelajaran Konfusius sangat kaya dan beraneka ragam. Dalam kitab Analek, beberapa penganut Konfusius dikatakan bisa meningkatkan amal kebaikan, kecakapan berbicara, berpemerintahan dan adab berbudaya [11:3]. Sebenarnya hal tersebut di atas bukanlah mata pelajaran dalam pengajaran Konfusius, tetapi dianggap sebagai dimensi pengembangan kehidupan manusia yang sangat dijunjung tinggi secara praktis dalam pengajaran Konfusius. Bisa disimpulkan bahwa ajaran Konfusius mengharapkan agar murid-muridnya bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, berbudaya, fasih dalam ber-bicara, dan berkomitmen dalam pelayanan publik. Namun, di antara mereka, hanya mereka yang sangat pintar saja yang bisa dianggap sebagai murid dengan pencapaian luar biasa. Dalam pengajarannya, Konfusius menetapkan empat perihal yang dianggap sebagai aturan pembelajaran: karya tulis, pelaksanaan pembelajaran, kesetiaan, dan kepercayaan [7:25]. Tingkah laku yang benar dianggap sangat penting dalam pedagogi Konfusius, tetapi penekanan utama pembelajaran bukanlah pada sikap dan kepercayaan. Ketepatan tingkah laku tanpa ditunjang oleh kebenaran sikap dan kepercayaan hanyalah suatu bentuk formalitas kosong. Tentunya, bagaimana seseorang melihat, mendengar, berbicara, dan bertingkah laku dalam segala hal dan keadaan lebih dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengembangkan diri [16:10], tetapi, hanya dengan melalui “ketegasan, resolusi, kesederhanaan, dan kesunyian” [13:27; Leys, hal. 65] yang bisa kita harapkan guna mencapai kesadaran penuh akan nilai kemanusiaan. Selain itu, “kesopanan, toleransi, kepercayaan, kecerdasan, dan kedermawanan” [17:16], adalah lima amalan yang bisa menempatkan kemanusiaan dalam ketepatan hubungan sosial yang harus diterapkan dalam segala bentuk sikap serta tindak tanduk.
Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan Konfusius tidak terikat pada pendidikan etika saja. Sebagai program pembelajaran yang menyeluruh dan terintegrasi demi untuk menjadi manusia seutuh- nya, pengajaran Konfusius meliputi segala sesuatu yang bisa kita sebut sebagai seni pendidikan liberal pada masa kini. The Six Classics menggambarkan visi kemanusiaan yang menyeluruh, sebuah visi yang menjembatani semua aspek dalam dunia sastra, musik, politik, sosial, sejarah, dan metafisika dari keberadaan manusia. Dalam kitab Analek, Konfusius memerintahkan anaknya dan juga murid-muridnya untuk belajar ‘berpuisi dan bersenandung ritual untuk mempelajari dasar-dasar bahasa dan menggunakan cara-cara hidup Konfusius (The Way). Konfusius memberikan contoh tiga raja bijak—Yao, Shun, dan Yu dalam naskah pembelajaran demi menunjukkan kekagumannya terhadap kebijaksanaan pemerintahan dari ketiga raja tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa membaca secara terus menerus tentang kitab ‘Perubahan’ membantu dirinya untuk terhindar dari tindakan salah selama hidup. Pengalaman pribadi Konfusius terhadap musik dan apresiasi diamnya terhadap Amanat dari Tuhan membuatnya bisa mencapai rasa pengembangan kemanusiaan yang berakar dari seni mendengar dan berdasarkan kehormatannya pada pengalaman masa lalu.
Oleh sebab itulah, prinsip dasar pendidikan Konfusius adalah keyakinan yang kuat bahwa hakikat manusia itu beragam dan memiliki multidimensi. Model pemikiran yang sempit bukan merupakan hakikat manusia, hal ini dianggap merendahkan dan keliru. Manusia bukanlah binatang dengan kemampuan berpikir, ataupun hanya pengguna alat, atau makhluk yang berbahasa, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang berestetika, bersosial, beretika, dan berspiritual. Kita bisa memahami keberadaan diri kita sendiri hanya apabila kita peduli akan badan kita, hati, pikiran, jiwa, dan ruh kita. Dari pemahaman pribadi bahwa manusia adalah makhluk individu kemudian mengacu kepada arah di mana manusia dihadapkan dengan hubungan-hubungan kompleks yang semakin berkembang, kemudian manusia menciptakan konsep rumah, komunitas, bangsa, dunia, bumi, dan kosmos berdasar- kan kepekaan dan kesadaran diri. Inilah mengapa kemanusiaan yang sebenarnya adalah tentang hubungan, dialog, psikologis, dan spiritual. Titik awal pendidikan harus diawali dengan hal nyata, yang menyangkut hidup manusia, di sini dan saat ini, meliputi pembelajaran tentang manusia yang mempunyai ikatan dari awal mulanya, terutama berupa ikatan afektif antara orang tua dan anaknya.
Implikasinya adalah, dalam sudut pandang modern, ikatan-ikatan sepeti ras, bahasa, jenis kelamin, umur, dan kepercayaan juga dianggap relevan. Sedikit banyak, setiap manusia ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang unik, yang berada pada waktu dan tempat tertentu, yang tidak pernah ada sebelumnya, dan yang tidak pernah akan ada lagi di masa mendatang. Manusia berbeda satu dengan lainnya seperti halnya perbedaan wajah masing-masing manusia. Para penganut Konfusius percaya bahwa manusia juga memiliki kesamaan dan sifat komunikatif alami yang serupa dalam hati dan pikiran kita. Hal inilah yang memungkinkan manusia untuk bisa bersama-sama melihat, mendengar, beremosi, menginginkan, merasakan, dan mengalami apa yang ada di dunia. Perpaduan antara persamaan dan perbedaan manusia memungkinkan kita menjadi apa yang seharusnya dimiliki manusia, bukan dengan cara mengorbankan ikatan-ikatan sebelumnya yang menjadikan kita manusia nyata dan seutuhnya. Ikatan-ikatan tersebut bisa di ubah menjadi alat untuk mewujudkan kesadaran diri. Inilah alasan mengapa hidup kita sebagai pelajar diperkaya oleh pertemuan dan ikatan dengan manusia lain yang beraneka ragam, yang memiliki keunikan masing-masing dan juga memiliki beberapa kesamaan informasi, ilmu, dan kebijaksanaan bersama. Perasaan, keinginan, motivasi, dan aspirasi kita boleh dianggap personal, tetapi bukanlah menjadi sesuatu yang individual atau privat. Kita sering mengungkapkan keprihatinan kita terhadap anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, kenalan, atau bahkan orang asing. Pengertian mereka yang penuh simpati tentang apa yang kita inginkan sangat berarti untuk kita.
Kehidupan manusia bersifat multidimensi. Usaha apa pun untuk mengurangi variasi kehidupan manusia baik secara fisik, mental, atau spiritual dianggap mengurangi produktivitas manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk psikologis, ekonomis, sosial, politis, historis, berseni, berbahasa, berbudaya, dan bermetafisika. Kesadaran penuh akan potensi manusia tidak akan pernah bisa hanya dari satu sisi. Konfusius percaya bahwa lingkungan yang harus dibuat untuk perkembangan diri manusia haruslah “harmonis meski tanpa kesamaan” [13:23]. Rasa hormat terhadap perbedaan sangat penting untuk perkembangan komunitas secara menyeluruh.
Etika Konfusius yang tersirat dalam pemikiran ini adalah etika yang diterapkan di segala lini kehidupan, motivasi yang murni, ketepatan situasi, keterikatan politik, tanggung jawab sosial, dan kesenangan. Pembelajaran etika ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia; yang memperlihatkan kerumitan suatu bentuk kehidupan. Nilai utama kitab Analek adalah ‘ren’ yang secara luas diartikan sebagai kebijakan, kebaikan, kemanusiaan, dan cinta. Saya menemukan bahwa terjemahan langsung karya Wingtsit Chan tentang etika di atas sebagai bentuk “kemanusiaan” adalah ide yang paling menarik dan masuk akal. Bagi Konfusius, kemanusiaan adalah bentuk kebajikan terpenting, seperti yang tersurat dalam kebenaran, kesopanan, kesetiaan, kepercayaan, kebajikan, perhatian, dan bentuk kesalehan dalam kebaktian terhadap orang tua. Kemanusiaan dianggap juga sebagai nilai menyeluruh yang bisa ditingkatkan dengan segala bentuk manifestasi dari keunggulan sifat manusia. Selama bertahun-tahun para pelajar Kongfusianisme beranggapan bahwa ‘ren’ pasti bersifat sosial, dan secara etimologis karakter ren berasal dari kombinasi antara gambaran tulis dan simbol-simbol kemanusiaan. Bisa dipahami kemudian apabila dalam sebuah esai, Peter Boodberg, seorang ahli kebudayaan Cina terkemuka, berpendapat bahwa cara paling tepat untuk mengartikan ren adalah sebuah “kerja sama kemanusiaan”. [“The Semasiology of Some Primary Confucian Concepts, Philosophy East and West 2, no. 4 (1953), 317-332]
Dalam kitab Analek, kemanusiaan sering dihubungkan dengan dan terkadang dibedakan dari kebijaksanaan (zhi) dan juga kepatuhan ritual (li, sopan santun). Hal ini mengacu pada kualitas dasar atas kenyataan dan kebenaran dari hakikat hidup seseorang secara nyata. Besar kemungkinan, kemudian, Konfusius melihat bahwa pembelajaran otentik itu adalah “pembelajaran demi diri sendiri”, hanya melalui kemandirian, pengembangan diri, dan kesadaran diri, manusia bisa dianggap sempurna. Dalam tradisi Konfusius, manusia adalah pusat hubungan baik secara personal maupun sosial. Dalam sebuah catatan bambu yang ditemukan di Guodian, huruf ren (kemanusiaan) ditulis dalam dua huruf: tubuh (shen) di bagian atas dan pikiran hati (xin) di bagian bawah. Gabungan kedua tulisan ini berarti bahwa kemanusiaan bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga mencakup hal yang bersifat personal.
Globalisasi ekonomi ditandai dengan berbagai rasionalisasi instrumen atau alat, ilmu pengetahuan, teknologi (terutama perkem- bangan informasi dan komunikasi), manajemen teknokratis, profesio- nalisme, materialisme, liberalisme, legitimasi keinginan, serta pilihan individu. “Manusia ekonomis” merupakan seekor hewan rasional yang sadar akan keinginannya sendiri, yang termotivasi dengan peningkatan kekayaan yang dimiliki, kekuatan dan pengaruh, serta berkomitmen untuk memaksimalkan keuntungan yang di dapat dalam pasar bebas yang di atur dalam perundang-undangan. Dia adalah perwujudan dari nilai-nilai modern, seperti kebebasan, rasionalitas, kesadaran terhadap hak-hak, etika kerja, pengetahuan, kompetensi teknis, kecerdasan kognitif, legalitas/masalah hukum, dan motivasi. Beberapa nilai penting kehidupan lainnya sebagai syarat terbentuknya solidaritas sosial bisa terdegradasi ke belakang atau terabaikan, seperti halnya keadilan, simpati, tanggung jawab, kesopanan dan kecerdasan etika.
Di dunia yang cenderung materialistis dan egosentris, kehausan manusia akan rasa spiritual sering mendukung terbentuknya eks- tremisme fundamental dan partikularisme eksklusif. Kemanusiaan dalam ajaran Konfusius, seperti yang diterangkan dalam kitab Analek, adalah suatu bentuk pendekatan seimbang dan terbuka terhadap tujuan kehidupan. Paham ini menawarkan pelatihan spiritual yang penting untuk pengembangan keilmuan pribadi dan merupakan bentuk awal dari kebajikan, serta sumber inspirasi yang selamanya memberikan arti pada proses pemahaman pribadi manusia.